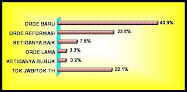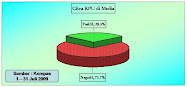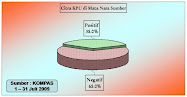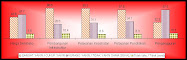Oleh: Abdul Hakim MS.
Suara Karya, 30 Desember 2006
Berbicara masalah etika politik, Aristoteles pernah menulis, identitas antara manusia yang baik dan warga Negara yang baik, hanya ada apabila negara sendiri baik (Politik III, 1973).
Penggalan tulisan itu kemudian dijabarkan oleh Frans Magnis Suseno dengan pengandaian; dalam kondisi sebuah negara yang buruk, seseorang akan akan mendapatkan label sebagai warga negara yang baik apabila mengikuti semua aturan-aturan negara yang buruk itu. Namun ketika seseorang itu tidak mengikuti semua aturan bobroknya negara tersebut, sebagai warga negara mungkin ia akan dicap sebagai pembangkang karena tidak mengikuti semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Akan tetapi sebagai manusia individu, ia merupakan manusia yang baik karena betul-betul bertanggung jawab dengan dirinya sendiri untuk tidak mengikuti kerusakan yang sedang berlangsung. (Etika Politik, 1999)
Lantas, apa hubungannya nukilan tulisan Aristoteles dan Frans Magnis ini dengan lembaga penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU)?
“Uang Kehormatan” Yang Tidak Hormat
Secara langsung, mungkin penggalan tulisan Aristoteles dan Frans Magnis di atas tidak ada kaitannya dengan KPU. Namun jika menilik tentang apa yang terjadi di KPU akhir-akhir ini, pernyataan kedua tokoh di atas, seolah menggiring kita untuk menengadah mencari korelasinya. Apalagi kalau dikaitkan dengan gaji yang diterima oleh penggawa-penggawa KPU saat ini. Gaji, yang diistilahkan sebagai “Uang Kehormatan” --karena KPU bukan pegawai negeri sehingga tidak menerima gaji-- benar-benar mengusik norma kita kala mengetahui duduk persoalannya.
Seperti kita tahu, di luar keberhasilannya menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum pada 2004 yang lalu, KPU dipenuhi dengan berbagai macam skandal korupsi dalam proses pengadaan barang-barang logistik untuk keperluan pesta demokrasi ini. Bahkan, berbagai macam skandal itu telah “melebarkan karpet merah” kepada sang ketua dan salah satu anggotanya ke jeruji besi. Selain itu, praktik kotor yang ada di KPU, masih menyisakan “adu jotos” yang keras antar anggotanya, yang salah satunya kini duduk di kabinet. Sedangkan yang lainnya harus rela menginap di rumah tahanan Mabes Polri.
Nah, disinilah pangkal persoalannya terjadi. Disaat semua anggota KPU ini sedang terjerat masalah hukum, bahkan sudah ada yang menerima keputusan tetap dari proses kasasi di Mahkamah Agung (MA) dan telah dinyatakan bersalah, ternyata “Uang Kehormatan” yang merupakan gaji tiap bulan itu, masih juga mereka terima.
Awalnya, saya juga agak ragu dan merasa tidak percaya ketika mendapatkan informasi ini. Namun saat dikonfirmasi ke bagian keuangan di KPU, ternyata informasi ini valid. “Uang Kehormatan” untuk terhukum masih diberikan. Alasannya, karena belum ada Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dari Presiden. Jadi, sang terpidana yang sudah berstatus sebagai terhukum pun, masih berhak dan bisa menikmati “Uang Kehormatan” itu dari balik jeruji penjara. Malah lebih hebat lagi, para terpidana ini juga masih menerima fasilitas sopir pribadi yang menjadi tenaga honorer dari KPU.
Sontak, saya begitu kaget. Dan ketika saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain, mereka juga tampak mengernyitkan kening kepala. “Apakah itu benar?” tanya salah satu kawan diskusi saya. “Jika memang itu sahih, sungguh tidak punya etika dan malu” lanjut kawan saya lagi. “Itu namanya Uang Kehormatan yang tidak terhormat” cetus kawan saya yang lain dengan ketus.
Pentingnya Etika Politik
Memang, secara hukum formal, sah-sah saja para pejabat KPU ini menerima “Uang Kehormatan” itu. Karena status mereka hingga saat ini masih sebagai anggota KPU. Ditambah lagi, jabatan mereka pun belum berakhir. Dan bagi mereka yang sedang terjerat masalah hukum, SK pemberhentian terhadap mereka pun belum keluar.
Namun bagaimana jika ditilik dari perspektif etika politik? Apakah masih wajar seorang pejabat, tetap menerima upah tatkala ia sudah tidak lagi dapat menjalankan tugas-tugasnya? Apakah etis seorang pejabat yang sudah tidak bisa lagi mengemban amanat kemudian masih menerima honor? Apalagi honor itu diberikan kepada mereka yang bestatus terpidana?
Disinilah kemudian etika politik mempunyai peran penting. Kewajaran yang disandang oleh para anggota KPU dalam menerima honor, menjadi risih karena mencederai rasa keadilan publik. Secara kasat mata, seharusnya, semua terpidana sudah tidak lagi bisa menerima fasilitas negara. Apalagi, gaji mereka dikutip dari perasan keringat pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Seharusnya, ketika seorang pejabat sudah ditetapkan sebagai orang yang bersalah oleh pengadilan, dengan sendirinya semua fasilitas yang menempel kepada dirinya juga harus ditiadakan.
Lebih jauh, Frans Magnis dalam buku Etika Politik 1999, menjelaskan, peran etika politik adalah mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia. Etika politik, berperan pada keadaan yang seharusnya. Keadaan ideal yang memang bila dilanggar tidak akan menyebaban jatuhnya hukuman fisik, melainkan hanya menghasilkan hukuman moral.
Jika dikorelasikan terhadap kasus “Uang Kehormatan” anggota KPU ini, sangsi fisik, memang tidak akan jatuh ketika para anggota ini tetap menerima honor. Namun secara moral, dimana letak tanggung jawab profesionalitas mereka sebagai manusia? Apakah para pejabat ini tidak merasa malu masih menikmati uang rakyat yang seharusnya tidak lagi mereka kenyam? Apalagi, status mereka sudah menjadi terpidana!
Namun, seperti banyak sudah kita dengar dari para pengamat politik, berbicara tentang etika politik itu seperti berteriak di gurun pasir. Meski telah mengeluarkan suara sekuat urat, tidak akan memberikan dampak apa-apa. Awalnya, mungkin suaranya akan menggema. Akan tetapi, lambat laun suaranya akan memudar perlahan-lahan dan lenyap sama sekali. Jadi, etika politik itu nonsens.
Meski begitu, setidak-tidaknya, hati kecil masih akan menggeliat resah. Seharusnya, negara sudah tidak lagi memberikan fasilitas kepada para terpidana. Seharusnya, para terpidana juga sadar bahwa mereka sudah tidak berhak lagi menerima uang masyarakat. Karena “Uang Kehormatan” itu dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang lainnya.
Melihat kondisi ini, Menjadi sebuah kepatutan untuk kita renungkan bersama-sama, dimanakah negara harus meletakkan etika politik sebagai asas untuk menggerakkan kapal besar seperti Indonesia?
Baca Selengkapnya...
Suara Karya, 30 Desember 2006
Berbicara masalah etika politik, Aristoteles pernah menulis, identitas antara manusia yang baik dan warga Negara yang baik, hanya ada apabila negara sendiri baik (Politik III, 1973).
Penggalan tulisan itu kemudian dijabarkan oleh Frans Magnis Suseno dengan pengandaian; dalam kondisi sebuah negara yang buruk, seseorang akan akan mendapatkan label sebagai warga negara yang baik apabila mengikuti semua aturan-aturan negara yang buruk itu. Namun ketika seseorang itu tidak mengikuti semua aturan bobroknya negara tersebut, sebagai warga negara mungkin ia akan dicap sebagai pembangkang karena tidak mengikuti semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Akan tetapi sebagai manusia individu, ia merupakan manusia yang baik karena betul-betul bertanggung jawab dengan dirinya sendiri untuk tidak mengikuti kerusakan yang sedang berlangsung. (Etika Politik, 1999)
Lantas, apa hubungannya nukilan tulisan Aristoteles dan Frans Magnis ini dengan lembaga penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU)?
“Uang Kehormatan” Yang Tidak Hormat
Secara langsung, mungkin penggalan tulisan Aristoteles dan Frans Magnis di atas tidak ada kaitannya dengan KPU. Namun jika menilik tentang apa yang terjadi di KPU akhir-akhir ini, pernyataan kedua tokoh di atas, seolah menggiring kita untuk menengadah mencari korelasinya. Apalagi kalau dikaitkan dengan gaji yang diterima oleh penggawa-penggawa KPU saat ini. Gaji, yang diistilahkan sebagai “Uang Kehormatan” --karena KPU bukan pegawai negeri sehingga tidak menerima gaji-- benar-benar mengusik norma kita kala mengetahui duduk persoalannya.
Seperti kita tahu, di luar keberhasilannya menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum pada 2004 yang lalu, KPU dipenuhi dengan berbagai macam skandal korupsi dalam proses pengadaan barang-barang logistik untuk keperluan pesta demokrasi ini. Bahkan, berbagai macam skandal itu telah “melebarkan karpet merah” kepada sang ketua dan salah satu anggotanya ke jeruji besi. Selain itu, praktik kotor yang ada di KPU, masih menyisakan “adu jotos” yang keras antar anggotanya, yang salah satunya kini duduk di kabinet. Sedangkan yang lainnya harus rela menginap di rumah tahanan Mabes Polri.
Nah, disinilah pangkal persoalannya terjadi. Disaat semua anggota KPU ini sedang terjerat masalah hukum, bahkan sudah ada yang menerima keputusan tetap dari proses kasasi di Mahkamah Agung (MA) dan telah dinyatakan bersalah, ternyata “Uang Kehormatan” yang merupakan gaji tiap bulan itu, masih juga mereka terima.
Awalnya, saya juga agak ragu dan merasa tidak percaya ketika mendapatkan informasi ini. Namun saat dikonfirmasi ke bagian keuangan di KPU, ternyata informasi ini valid. “Uang Kehormatan” untuk terhukum masih diberikan. Alasannya, karena belum ada Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dari Presiden. Jadi, sang terpidana yang sudah berstatus sebagai terhukum pun, masih berhak dan bisa menikmati “Uang Kehormatan” itu dari balik jeruji penjara. Malah lebih hebat lagi, para terpidana ini juga masih menerima fasilitas sopir pribadi yang menjadi tenaga honorer dari KPU.
Sontak, saya begitu kaget. Dan ketika saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain, mereka juga tampak mengernyitkan kening kepala. “Apakah itu benar?” tanya salah satu kawan diskusi saya. “Jika memang itu sahih, sungguh tidak punya etika dan malu” lanjut kawan saya lagi. “Itu namanya Uang Kehormatan yang tidak terhormat” cetus kawan saya yang lain dengan ketus.
Pentingnya Etika Politik
Memang, secara hukum formal, sah-sah saja para pejabat KPU ini menerima “Uang Kehormatan” itu. Karena status mereka hingga saat ini masih sebagai anggota KPU. Ditambah lagi, jabatan mereka pun belum berakhir. Dan bagi mereka yang sedang terjerat masalah hukum, SK pemberhentian terhadap mereka pun belum keluar.
Namun bagaimana jika ditilik dari perspektif etika politik? Apakah masih wajar seorang pejabat, tetap menerima upah tatkala ia sudah tidak lagi dapat menjalankan tugas-tugasnya? Apakah etis seorang pejabat yang sudah tidak bisa lagi mengemban amanat kemudian masih menerima honor? Apalagi honor itu diberikan kepada mereka yang bestatus terpidana?
Disinilah kemudian etika politik mempunyai peran penting. Kewajaran yang disandang oleh para anggota KPU dalam menerima honor, menjadi risih karena mencederai rasa keadilan publik. Secara kasat mata, seharusnya, semua terpidana sudah tidak lagi bisa menerima fasilitas negara. Apalagi, gaji mereka dikutip dari perasan keringat pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Seharusnya, ketika seorang pejabat sudah ditetapkan sebagai orang yang bersalah oleh pengadilan, dengan sendirinya semua fasilitas yang menempel kepada dirinya juga harus ditiadakan.
Lebih jauh, Frans Magnis dalam buku Etika Politik 1999, menjelaskan, peran etika politik adalah mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia. Etika politik, berperan pada keadaan yang seharusnya. Keadaan ideal yang memang bila dilanggar tidak akan menyebaban jatuhnya hukuman fisik, melainkan hanya menghasilkan hukuman moral.
Jika dikorelasikan terhadap kasus “Uang Kehormatan” anggota KPU ini, sangsi fisik, memang tidak akan jatuh ketika para anggota ini tetap menerima honor. Namun secara moral, dimana letak tanggung jawab profesionalitas mereka sebagai manusia? Apakah para pejabat ini tidak merasa malu masih menikmati uang rakyat yang seharusnya tidak lagi mereka kenyam? Apalagi, status mereka sudah menjadi terpidana!
Namun, seperti banyak sudah kita dengar dari para pengamat politik, berbicara tentang etika politik itu seperti berteriak di gurun pasir. Meski telah mengeluarkan suara sekuat urat, tidak akan memberikan dampak apa-apa. Awalnya, mungkin suaranya akan menggema. Akan tetapi, lambat laun suaranya akan memudar perlahan-lahan dan lenyap sama sekali. Jadi, etika politik itu nonsens.
Meski begitu, setidak-tidaknya, hati kecil masih akan menggeliat resah. Seharusnya, negara sudah tidak lagi memberikan fasilitas kepada para terpidana. Seharusnya, para terpidana juga sadar bahwa mereka sudah tidak berhak lagi menerima uang masyarakat. Karena “Uang Kehormatan” itu dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang lainnya.
Melihat kondisi ini, Menjadi sebuah kepatutan untuk kita renungkan bersama-sama, dimanakah negara harus meletakkan etika politik sebagai asas untuk menggerakkan kapal besar seperti Indonesia?