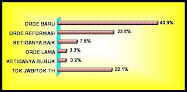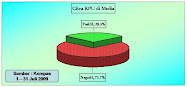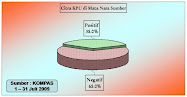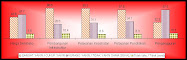Melihat perkembangan demokrasi kita, memang menimbulkan kebanggaan. Saya melihat, demokrasi kita saat ini, mungkin bisa dikatakan yang paling demokratis. Berbagai sendi praktik bernegara kita, tak bisa lepas dari pengawasan pihak lain, begitupun dengan pemerintah. PDI-P memproklamirkan diri sebagai oposisi, salah satu stakeholder yang wajib ada dalam tatanan demokrasi.
Mungkin yang menggelitik hati, apakah oposisi harus selalu berbeda?
Pertanyaan ini muncul dibenak saya tatkala PDIP kembali menolak usul Presiden yang meminta agar pengesahan RUU Perampasan Aset bisa dilakukan oleh DPR pada tahun 2008. Usulan presiden ini dianggap oleh PDIP hanya sebagai salah satu cara agar pemerintah kelihatan serius dalam pemberantasan korupsi. Yang lebih lucu, salah satu tokoh PDIP mengatakan yang penting political will. Ibarat kita mau ke Singapura dalam waktu 1 jam, mungkinkah kita bisa sampai disana tanpa menumpang pesawat? Atau dalam arti kata lain, mungkinkah kita dapat meberantas korupsi tanpa ada alat UU yang komprehensif?
Selama ini, penyidik kita tak punya kuasa untuk menyita aset-aset negara yang dikorupsi sebelum kasusnya mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun begitu inkracht, aset-aset negara yang telah dikorupsi sudah lenyap. Kemudian, hasil apa yang akan diperoleh lembaga peradilan jika semua kasus terjadi seperti ini? Jawabannya pasti, NIHIL.
Tentu, dengan adanya UU Perampasan Aset, penyidik tak lagi harus menunggu untuk menyita aset-aset negara yang diduga dikorupsi. Dengan adanya UU ini, jaminan aset negara yang dikorupsi bisa kembali menjadi sangat tinggi. Menjadi hal yang ganjil apabila usulan seperti ini disanggah. Padahal dinegara lain, UU semacam ini sudah menjadi kebutuhan wajib.
Kiranya, PDIP memposisikan diri sebagai oposisi jangan kemudian asal beda. Tidak bermaksud membela pemerintah, namun apa yang diupayakan oleh Presiden ini merupakan langkah baik untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, PDI-P harus bisa memilah-milah dalam posisi mana harus berbeda dan dalam situasi apa PDI-P harus bisa bekerja sama. Jika kondisinya demikian, sepertinya demikrasi kita akan berjalan lebih indah dengan berujung pada kebaikan masyarakat kita semua.
Baca Selengkapnya...
Mungkin yang menggelitik hati, apakah oposisi harus selalu berbeda?
Pertanyaan ini muncul dibenak saya tatkala PDIP kembali menolak usul Presiden yang meminta agar pengesahan RUU Perampasan Aset bisa dilakukan oleh DPR pada tahun 2008. Usulan presiden ini dianggap oleh PDIP hanya sebagai salah satu cara agar pemerintah kelihatan serius dalam pemberantasan korupsi. Yang lebih lucu, salah satu tokoh PDIP mengatakan yang penting political will. Ibarat kita mau ke Singapura dalam waktu 1 jam, mungkinkah kita bisa sampai disana tanpa menumpang pesawat? Atau dalam arti kata lain, mungkinkah kita dapat meberantas korupsi tanpa ada alat UU yang komprehensif?
Selama ini, penyidik kita tak punya kuasa untuk menyita aset-aset negara yang dikorupsi sebelum kasusnya mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun begitu inkracht, aset-aset negara yang telah dikorupsi sudah lenyap. Kemudian, hasil apa yang akan diperoleh lembaga peradilan jika semua kasus terjadi seperti ini? Jawabannya pasti, NIHIL.
Tentu, dengan adanya UU Perampasan Aset, penyidik tak lagi harus menunggu untuk menyita aset-aset negara yang diduga dikorupsi. Dengan adanya UU ini, jaminan aset negara yang dikorupsi bisa kembali menjadi sangat tinggi. Menjadi hal yang ganjil apabila usulan seperti ini disanggah. Padahal dinegara lain, UU semacam ini sudah menjadi kebutuhan wajib.
Kiranya, PDIP memposisikan diri sebagai oposisi jangan kemudian asal beda. Tidak bermaksud membela pemerintah, namun apa yang diupayakan oleh Presiden ini merupakan langkah baik untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya, PDI-P harus bisa memilah-milah dalam posisi mana harus berbeda dan dalam situasi apa PDI-P harus bisa bekerja sama. Jika kondisinya demikian, sepertinya demikrasi kita akan berjalan lebih indah dengan berujung pada kebaikan masyarakat kita semua.