Pandangan bangsa ini tertuju ke 9 April 2009. Pemilu legislatif akan digelar. Hingga detik akhir hari H penyontrengan, kesemrawutan persiapan dan berbagai persoalan terus menyembul kepermukaan. DPT fiktif belum terselesaikan. KPPS masih banyak yang belum menerima kertas dan bilik suara. Potensi konflik saat menentukan keabsahan surat suara pada penghitungan suara cukup tinggi. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT kemudian datang ke TPS belum tahu nasibnya. Dan sejumlah persoalan lain yang rentan menimbulkan pergesekan antar pendukung parpol dan caleg pun terus mengancam. Bisa dibilang, pemilu kali ini cukup menghawatirkan!
Kondisi di atas, berbanding terbalik dengan asa pemilih kita. Dari survei yang dilakukan Indo Barometer pada Desember 2008, mayoritas pemilih (56.3%) yakin bahwa pemilu 2009 secara umum akan mengantarkan Indonesia kekehidupan yang lebih baik. Sekitar 34.9 persen menjawab tidak yakin. Dan 8.7 persen menjawab tidak tahu. Di bidang ekonomi, politik, dan hukum, mayoritas pemilih juga yakin bahwa pemilu 2009 akan membawa kekehidupan yang lebih baik (angkanya selalu di atas 50%). Pertanyaan relevan yang kemudian muncul, apakah keyakinan pemilih ini akan terjadi jika proses pemilunya dipertanyakan legitimasinya karena salah urus, banyak menimbulkan perdebatan dan menyeruakkan potensi konflik yang cukup tinggi?
Suara tak sah
Ancaman dan kekhawatiran tertinggi pemilu 2009 adalah potensi golput. Ignas Kleden menulis, ada dua kemungkinan seseorang memilih menjadi golput. Pertama, opsi negatif, yaitu ketika dia merasa tidak mempunyai alasan yang cukup untuk turut memilih dalam pemilu. Kedua, opsi positif, yaitu ketika seseorang merasa mempunyai alasan yang cukup untuk tidak turut memilih.
Dalam konteks Indonesia dan pemilu 2009 khususnya, dua kemungkinan yang diungkapkan oleh Kleden rasanya kurang mencukupi. Ada kemungkinan lain yang menyebabkan seseorang menjadi golput, antara lain; pertama, dia punya alasan untuk memilih dan dia mau menggunakan hak pilihnya, akan tetapi namanya tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT, kemungkinan besar akan malas datang ke TPS, kecuali ia mempunyai kesadaran yang memadai akan arti memilih.
KPU punya argumentasi tersendiri terhadap kemungkinan ini. Menurut KPU, yang tidak terdaftar dalam DPT, agar dia tidak menjadi golput, ia bisa datang dengan membawa identitas diri agar bisa memilih. Pertanyaannya, adakah kertas suara cadangan untuk mereka? Seberapa banyak kertas suara cadangan yang disediakan oleh KPU? Padahal, hingga detik ini, kertas suara yang dibagikan ke TPS oleh KPU, jumlahnya sama persis dengan jumlah nama yang ada di DPT. Apakah pemilih yang masuk kategori ini bisa memilih meski sudah datang ke TPS ketika tidak ada lagi kertas suara?
Kedua, pemilih mau datang ke TPS dan namanya telah tertera di DPT, ia juga telah memberikan suaranya untuk caleg dan partai pilihannya, akan tetapi pemberian suaranya dianggap tidak sah. Potensi golput yang masuk dalam kategori inilah yang sangat tinggi. Berdasarkan pengalaman pemilu 2004, jumlah suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR-RI mencapai 10.957.925 pemilih atau 7.4 persen dari DPT waktu itu. Angka ini lebih besar daripada jumlah DPT pemilu 2009 untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta sekitar 7.026.772. Lebih ekstrim lagi, Jumlah itu masih lebih besar dibandingkan jumlah DPT dari dapil NAD, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Kepulauan Riau yang mencapai 10.597.740. Tentu ini ancaman serius.
Padahal, sistem pemberian suara pada pemilu 2004 tidak terlalu rumit, yaitu hanya mencoblos. Jumlah partai politik perserta pemilu juga tak terlalu banyak, 24 parpol. Sedangkan pada pemilu 2009, mekanisme pemberian suara masih cukup membingungkan para pemilih, yakni boleh mencontreng/centang, mencoblos, memberi tanda garis, akan tetapi tidak boleh melingkari. Belum lagi jumlah partai yang mencapai 38 parpol dan kertas suara raksasa yang ukurannya lebih besar daripada bilik suaranya. Faktor-faktor ini menjadi pemicu besarnya suara golput dari suara yang tidak sah ini.
Jadi jika dibuat klasifikasi, ancaman golput pada pemilu 2009 datang dari dua arah. Pertama, suara golput dari pemilih yang tidak mau datang ke TPS karena sudah atau belum mempunyai alasan seperti yang didikotomikan oleh Ignas Kleden. Kedua, suara golput yang datang karena buruknya teknis administrasi yang dibuat oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dalam menyukseskan pesta lima tahunan ini, alias golput administratif.
Legitimasi
Hakikat pemilu yang sebenarnya adalah meletakkan legitimasi kepada para pembuat kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif. Dan kita telah melakukan pemilu secara nasional sebanyak 12 kali. Dua kali untuk memilih anggota DPR dan anggota Badan Konstituante pada bulan September dan Desember 1955. Enam kali pada zaman Orde Baru dalam rentang waktu 1971 – 1997. Dan empat kali pada saat reformasi, yakni memilih anggota DPR pada 1999, memilih anggota DPR pada 2004, dan dua kali untuk memilih presiden dan wakil presiden pada 2004.
Dengan pengalaman sebanyak itu, idealnya kita telah mempunyai sistem kepemiluan yang cukup baik. Akan tetapi, hingga detik ini sepertinya jauh panggang dari api. Kita tetap terseok-seok untuk menata sistem kepemiluan kita. Kenapa demikian?
Tak mudah menjawab pertanyaan itu dengan argumentasi singkat. Kita tak bisa menyalahkan hanya satu pihak terkait dengan bermasalahnya kepemiluan kita. Persoalan mendasar kenapa negeri ini setiap kali melaksanakan pemilu tidak pernah beres, terletak pada proses pendataan penduduk yang tidak baik. Hingga kini data BPS yang seharusnya bisa dijadikan rujukan valid untuk menetapkan calon pemilih, tak memberi banyak harapan. Di luar itu, ketidakberesan data BPS, dibarengi juga dengan tak adanya inisiatif pembenahan serius dalam pendataan ulang pemilih setiap kali pemilu diselenggarakan oleh KPU. Implikasinya, sejak tahun 1955 hingga 2009 persoalan pemilu berkutat ditempat yang sama, amburadulnya DPT!
Disamping masalah DPT, para perancang UU Pemilu (yang terdiri atas para petinggi partai terpilih di DPR) tak pernah berpikir panjang. Kepentingan sesaat lebih dominan daripada semangat membangun sistem kepemiluan dan kepartaian yang lebih baik. Menjadi tak heran, setiap pemilu menjelang pun dibarengi dengan UU Pemilu yang baru. Implikasinya, ketaatan dengan sistem yang telah disepakati pada pemilu sebelumnya menjadi hilang begitu saja. Contoh sederhana adalah pengabaian sistem electoral threshold. Partai yang seharusnya tak boleh mengikuti pemilu 2009, tetap bisa ikut dengan akal-akalan asal dapat kursi di DPR. Sistem baru pun dibuat dengan nama parliamentary threshold.
Kondisi di atas, diperparah oleh lemahnya interpretasi penyelenggara KPU terhadap UU Pemilu. Kasus-kasus yang menerabas keadilan publik muncul tanpa henti. Ambil sebagai contoh munculnya surat edaran KPU No. 62/KPU/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang sumbangan kampanye perorangan dan organisasi yang boleh di atas angka yang telah ditetapkan UU Pemilu. Belum lagi Peraturan KPU No.15 tahun 2009 yang satu diantara isinya mengatur mekanisme undian dalam menentukan caleg terpilih. Kemudian juga peraturan KPU dalam mengartikan pemberian satu kali tanda di kertas suara, apa menyontreng/centang, coblos dan sebagainya. Ini semua semakin memperburuk wajah kepemiluan kita!
Poin yang ingin dikemukakan adalah, jika pemilu terus dikerubuti masalah, bukankah legitimasinya akan dipertanyakan? Dan dari pemimpin yang dipertanyakan legitimasinya, akankah kita dapat menaruh harapan kepada mereka? Padahal para pemilih kita punya harapan besar pada pemilu kali ini. Tentu kondisi ini merupakan sebuah paradoks.
Kondisi di atas, berbanding terbalik dengan asa pemilih kita. Dari survei yang dilakukan Indo Barometer pada Desember 2008, mayoritas pemilih (56.3%) yakin bahwa pemilu 2009 secara umum akan mengantarkan Indonesia kekehidupan yang lebih baik. Sekitar 34.9 persen menjawab tidak yakin. Dan 8.7 persen menjawab tidak tahu. Di bidang ekonomi, politik, dan hukum, mayoritas pemilih juga yakin bahwa pemilu 2009 akan membawa kekehidupan yang lebih baik (angkanya selalu di atas 50%). Pertanyaan relevan yang kemudian muncul, apakah keyakinan pemilih ini akan terjadi jika proses pemilunya dipertanyakan legitimasinya karena salah urus, banyak menimbulkan perdebatan dan menyeruakkan potensi konflik yang cukup tinggi?
Suara tak sah
Ancaman dan kekhawatiran tertinggi pemilu 2009 adalah potensi golput. Ignas Kleden menulis, ada dua kemungkinan seseorang memilih menjadi golput. Pertama, opsi negatif, yaitu ketika dia merasa tidak mempunyai alasan yang cukup untuk turut memilih dalam pemilu. Kedua, opsi positif, yaitu ketika seseorang merasa mempunyai alasan yang cukup untuk tidak turut memilih.
Dalam konteks Indonesia dan pemilu 2009 khususnya, dua kemungkinan yang diungkapkan oleh Kleden rasanya kurang mencukupi. Ada kemungkinan lain yang menyebabkan seseorang menjadi golput, antara lain; pertama, dia punya alasan untuk memilih dan dia mau menggunakan hak pilihnya, akan tetapi namanya tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT, kemungkinan besar akan malas datang ke TPS, kecuali ia mempunyai kesadaran yang memadai akan arti memilih.
KPU punya argumentasi tersendiri terhadap kemungkinan ini. Menurut KPU, yang tidak terdaftar dalam DPT, agar dia tidak menjadi golput, ia bisa datang dengan membawa identitas diri agar bisa memilih. Pertanyaannya, adakah kertas suara cadangan untuk mereka? Seberapa banyak kertas suara cadangan yang disediakan oleh KPU? Padahal, hingga detik ini, kertas suara yang dibagikan ke TPS oleh KPU, jumlahnya sama persis dengan jumlah nama yang ada di DPT. Apakah pemilih yang masuk kategori ini bisa memilih meski sudah datang ke TPS ketika tidak ada lagi kertas suara?
Kedua, pemilih mau datang ke TPS dan namanya telah tertera di DPT, ia juga telah memberikan suaranya untuk caleg dan partai pilihannya, akan tetapi pemberian suaranya dianggap tidak sah. Potensi golput yang masuk dalam kategori inilah yang sangat tinggi. Berdasarkan pengalaman pemilu 2004, jumlah suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR-RI mencapai 10.957.925 pemilih atau 7.4 persen dari DPT waktu itu. Angka ini lebih besar daripada jumlah DPT pemilu 2009 untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta sekitar 7.026.772. Lebih ekstrim lagi, Jumlah itu masih lebih besar dibandingkan jumlah DPT dari dapil NAD, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Kepulauan Riau yang mencapai 10.597.740. Tentu ini ancaman serius.
Padahal, sistem pemberian suara pada pemilu 2004 tidak terlalu rumit, yaitu hanya mencoblos. Jumlah partai politik perserta pemilu juga tak terlalu banyak, 24 parpol. Sedangkan pada pemilu 2009, mekanisme pemberian suara masih cukup membingungkan para pemilih, yakni boleh mencontreng/centang, mencoblos, memberi tanda garis, akan tetapi tidak boleh melingkari. Belum lagi jumlah partai yang mencapai 38 parpol dan kertas suara raksasa yang ukurannya lebih besar daripada bilik suaranya. Faktor-faktor ini menjadi pemicu besarnya suara golput dari suara yang tidak sah ini.
Jadi jika dibuat klasifikasi, ancaman golput pada pemilu 2009 datang dari dua arah. Pertama, suara golput dari pemilih yang tidak mau datang ke TPS karena sudah atau belum mempunyai alasan seperti yang didikotomikan oleh Ignas Kleden. Kedua, suara golput yang datang karena buruknya teknis administrasi yang dibuat oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dalam menyukseskan pesta lima tahunan ini, alias golput administratif.
Legitimasi
Hakikat pemilu yang sebenarnya adalah meletakkan legitimasi kepada para pembuat kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif. Dan kita telah melakukan pemilu secara nasional sebanyak 12 kali. Dua kali untuk memilih anggota DPR dan anggota Badan Konstituante pada bulan September dan Desember 1955. Enam kali pada zaman Orde Baru dalam rentang waktu 1971 – 1997. Dan empat kali pada saat reformasi, yakni memilih anggota DPR pada 1999, memilih anggota DPR pada 2004, dan dua kali untuk memilih presiden dan wakil presiden pada 2004.
Dengan pengalaman sebanyak itu, idealnya kita telah mempunyai sistem kepemiluan yang cukup baik. Akan tetapi, hingga detik ini sepertinya jauh panggang dari api. Kita tetap terseok-seok untuk menata sistem kepemiluan kita. Kenapa demikian?
Tak mudah menjawab pertanyaan itu dengan argumentasi singkat. Kita tak bisa menyalahkan hanya satu pihak terkait dengan bermasalahnya kepemiluan kita. Persoalan mendasar kenapa negeri ini setiap kali melaksanakan pemilu tidak pernah beres, terletak pada proses pendataan penduduk yang tidak baik. Hingga kini data BPS yang seharusnya bisa dijadikan rujukan valid untuk menetapkan calon pemilih, tak memberi banyak harapan. Di luar itu, ketidakberesan data BPS, dibarengi juga dengan tak adanya inisiatif pembenahan serius dalam pendataan ulang pemilih setiap kali pemilu diselenggarakan oleh KPU. Implikasinya, sejak tahun 1955 hingga 2009 persoalan pemilu berkutat ditempat yang sama, amburadulnya DPT!
Disamping masalah DPT, para perancang UU Pemilu (yang terdiri atas para petinggi partai terpilih di DPR) tak pernah berpikir panjang. Kepentingan sesaat lebih dominan daripada semangat membangun sistem kepemiluan dan kepartaian yang lebih baik. Menjadi tak heran, setiap pemilu menjelang pun dibarengi dengan UU Pemilu yang baru. Implikasinya, ketaatan dengan sistem yang telah disepakati pada pemilu sebelumnya menjadi hilang begitu saja. Contoh sederhana adalah pengabaian sistem electoral threshold. Partai yang seharusnya tak boleh mengikuti pemilu 2009, tetap bisa ikut dengan akal-akalan asal dapat kursi di DPR. Sistem baru pun dibuat dengan nama parliamentary threshold.
Kondisi di atas, diperparah oleh lemahnya interpretasi penyelenggara KPU terhadap UU Pemilu. Kasus-kasus yang menerabas keadilan publik muncul tanpa henti. Ambil sebagai contoh munculnya surat edaran KPU No. 62/KPU/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang sumbangan kampanye perorangan dan organisasi yang boleh di atas angka yang telah ditetapkan UU Pemilu. Belum lagi Peraturan KPU No.15 tahun 2009 yang satu diantara isinya mengatur mekanisme undian dalam menentukan caleg terpilih. Kemudian juga peraturan KPU dalam mengartikan pemberian satu kali tanda di kertas suara, apa menyontreng/centang, coblos dan sebagainya. Ini semua semakin memperburuk wajah kepemiluan kita!
Poin yang ingin dikemukakan adalah, jika pemilu terus dikerubuti masalah, bukankah legitimasinya akan dipertanyakan? Dan dari pemimpin yang dipertanyakan legitimasinya, akankah kita dapat menaruh harapan kepada mereka? Padahal para pemilih kita punya harapan besar pada pemilu kali ini. Tentu kondisi ini merupakan sebuah paradoks.








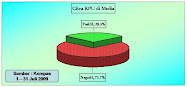
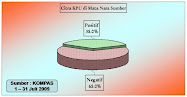
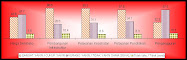


No comments:
Post a Comment