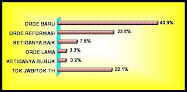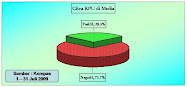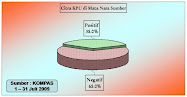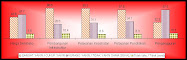Oleh : Abdul Hakim MS.
Koran Sindo
 UU Pilpres belum selesai hingga kini. Masalah kapan pejabat negara harus mengundurkan diri jika menjadi capres/cawapres, masalah rangkap jabatan serta persoalan ambang batas perolehan suara partai untuk mengajukan capres/cawapres masih menjadi kendala. Meski begitu, ada satu kesimpulan awal yang bisa dihadirkan terhadap UU Pilpres yang akan diundangkan, yakni pemilu 2009 mendatang tampaknya akan sulit menghadirkan calon presiden muka baru. Konstelasi tetap akan diramaikan oleh wajah lama seperti SBY, Megawati, Amin Rais, Wiranto serta tokoh-tokoh ”tua” lainnya. Dan pertarungan pun sepertinya akan mengerucut pada sosok SBY dan Megawati. Karena hingga kini, hanya kedua tokoh itulah yang paling populer memenangkan pilihan presiden berdasarkan hasil berbagai lembaga survei.
UU Pilpres belum selesai hingga kini. Masalah kapan pejabat negara harus mengundurkan diri jika menjadi capres/cawapres, masalah rangkap jabatan serta persoalan ambang batas perolehan suara partai untuk mengajukan capres/cawapres masih menjadi kendala. Meski begitu, ada satu kesimpulan awal yang bisa dihadirkan terhadap UU Pilpres yang akan diundangkan, yakni pemilu 2009 mendatang tampaknya akan sulit menghadirkan calon presiden muka baru. Konstelasi tetap akan diramaikan oleh wajah lama seperti SBY, Megawati, Amin Rais, Wiranto serta tokoh-tokoh ”tua” lainnya. Dan pertarungan pun sepertinya akan mengerucut pada sosok SBY dan Megawati. Karena hingga kini, hanya kedua tokoh itulah yang paling populer memenangkan pilihan presiden berdasarkan hasil berbagai lembaga survei.
Melihat kondisi di atas, menjadi cukup menarik apabila kemudian memfokuskan perhatian terhadap pasangan yang akan mendampingi mereka. Karena posisi wakil presiden adalah kartu truf. Ibarat dua mata pisau, posisinya bisa mengangkat pun bisa juga menjatuhkan. Kita mungkin bisa sedikit berkaca dari pemilu AS yang kini sedang berlangsung. Jauh hari ketika Obama dan Maccain masih berjuang memenangkan konvensi dipartai masing-masing, Obama selalu unggul diberbagai hasil jajak pendapat. Namun setelah Maccain menggandeng Sarah Palin dan Obama menggamit Joe Biden, konstelasi langsung berubah. Obama kini tertinggal, meski tak drastis. Artinya, unsur Sarah Palin bisa mengangkat popularitas Maccain dan Joe Biden tak terlalu berpengaruh terhadap popularitas Obama. Bagaimana dengan Indonesia? Siapa wapres yang berpotensi mengangkat pasangannya pada pemilu 2009 mendatang?
Dalam memilih pasangan, hemat saya, seorang calon presiden akan memperhatikan dua aspek pokok. Pertama, wakil yang akan dipilih harus bisa membantu untuk memenangkan general election, karena itu tujuan utama. Namun hal kedua yang tak kalah penting adalah, pasangan tersebut harus bisa mendampingi sang presiden dalam hal apapun ketika mereka telah terpilih.
Dalam konteks mencari calon wakil presiden ideal yang memenuhi dua kriteria di atas, setidak-tidaknya capres harus memperhatikan filosofi lima jari. Pertama, wakil yang dipilih harus seperti jempol. Artinya pasangan yang akan digamit harus hebat. Hebat disini diartikan mempunyai bibit, bebet dan bobot yang baik. Bibit berarti ia harus berasal dari partai yang kuat guna mendukung kebijakan-kebijakan di parlemen. Ia juga harus populer sehingga dapat membantu mengangkat popularitas pasangannya dan mempunyai dana yang cukup untuk kampanye. Bebet berarti ia mempunyai lingkungan yang loyal atau dalam bahasa lain mempunyai basis konstituen yang fanatik. Bobot diartikan harus memiliki nilai pribadi yang handal seperti attitude yang baik, pengetahuan yang luas dan konsep pengendalian diri yang mumpuni.
Kriteria jari selanjutnya dalam mencari wakil, ia harus bisa seperti kelingking. Arti kelingking disini adalah ia harus dapat menjadi negasi. Ia harus berani mendebat keputusan yang dianggap menyimpang. Meski begitu, sang wakil harus tetap rendah hati untuk bisa menemukan sintesis yang baik. Karena jika tak rendah hati seperti kelingking, pasangan tersebut bisa bubar ditengah jalan.
Ketiga, pasangan yang akan digamit juga harus bisa seperti jari telunjuk. Ia bisa membimbing dan menjadi guide yang profesional. Ia tak hanya mendebat, melainkan dapat menunjukkan jalan alternatif bagi perjalanan keduanya. Keempat, ia harus bisa menjadi seperti jari manis. Artinya ia mau berkomitmen untuk saling menerima kekurangan masing-masing. Implikasinya, keduanya akan menjadi pasangan yang understanding dan saling melengkapi cela kelemahan yang ada. Ujungnya, ia tak akan jalan sendiri-sendiri yang bermuara pada ”perceraian”.
Kelima, wakil yang dipilih harus menjadi seperti jari tengah. Artinya, pasangan harus berkomitmen mendahulukan persoalan pasangan dan menjaga agar pasangan tersebut bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan selama 5 tahun kedepan. Keduanya akan saling berkomitmen menyelesaikan persoalan mereka terlebih dahulu sebelum lari ke masalah negara yang lebih luas. Harapannya, keduanya akan selalu harmonis dalam meregulasi kehidupan negara yang sangat berat.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kira-kira siapa cawapres Indonesia yang bisa memenuhi kriteria-kriteria diatas?
JK, Hidayat, Wiranto dan Prabowo
Kala survei dilakukan untuk mengetahui nama-nama potensial untuk kedudukan sebagai calon wakil presiden, nama yang beredar di bursa memang lebih beragam dibandingkan dengan kandidat calon presiden. Survei Indo Barometer pada Juni 2008 menunjukkan hal itu. Dalam pertanyaan terbuka untuk nama cawapres, ada 10 nama muncul dengan dukungan suara terbanyak. Mereka adalah Sri Sultan HB X (19,9%), Jusuf Kalla (12,3%), Hidayat Nur Wahid (10,7%), Yusril Ihza Mahendra (4,9%); Prabowo Subianto (4,9%), Akbar Tanjung (4,6%), Hasyim Muzadi(4%), Din Syamsuddin (3,3%), Agung Laksono (2,8%) dan Aburizal Bakrie (2,2%). Dan sebetulnya masih banyak lagi nama lainnya. Lantas, siapa diantara mereka yang paling potensial?
Jika merujuk kriteria filosofi lima jari yang telah tertera sebelumnya, tentu tak semua nama di atas masuk kategori potensial. Hemat saya, tingkatan potensial bisa dibuat dalam kelompok-kelompok bertangga. Kelompok pertama ada nama Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid, Wiranto, Yusril Ihza Mahendra dan Prabowo. Kelompok kedua ada nama Sultan HB X dan Akbar Tandjung. Serta kelompok ketiga adalah nama-nama lainnya. atas dasar apa pengeleompokan itu?
Kelompok pertama dimasukkan dengan indikator, nama-nama itu memenuhi 4 unsur utama, yakni mempunyai kendaraan politik cukup potensial pada pemilu 2009 mendatang dan kans untuk menjadi presiden masih diragukan. Selain kendaraan politik, dana untuk berkampanye juga tak menjadi persoalan bagi kelompok pertama ini. Dalam hal popuaritas, kelompok ini juga cukup menjanjikan bisa mengatrol pasangannya. Dalam hal pengetahuan dan pengalaman memimpin, kelompok pertama ini telah mengenyam banyak pengalaman di birokrasi.
Dibawah kelompok pertama ini ada nama Sultan HB X dan Akbar Tandjung. Kenapa dua nama ini masuk kelompok kedua? Padahal popularitas HB X malah yang tertinggi diantara cawapres lainnya? Hemat saya, hal ini lantaran keduanya hingga kini belum mau secara tegas berafiliasi dengan salah satu partai yang ada. Padahal, syarat mutlak untuk mendapatkan tempat wakil presiden adalah koalisi untuk share kekuasaan. Dan jika keduanya hingga beberapa waktu kedepan tak menentukan kendaraan politik, rasanya cukup sulit untuk bisa digandeng capres yang telah mapan. Karena mereka tak mungkin lagi mendapat dukungan dari Golkar yang sudah pasti akan mengusung ketua umum mereka, Jusuf Kalla.
Kelompok paling akhir adalah nama-nama yang saat ini sedang sibuk mengiklankan diri atau bahkan nama yang belum muncul sama sekali. Sebut saja Sutrisno Bachir, Rizal Mallarangeng, Fajroel Rahman dll. Kenapa nama-nama ini? Itu tak lain karena mereka dalam hal popularitas masih sangat minim. Yang menjadi catatan lagi, sosok Sutrisno Bachir, meski iklan di media massa sangat gencar, tapi penilaian publik masih cukup rendah. Hal ini karena ia belum begitu konkrit menunjukkan peran-aktif ditengah-tengah masyarakat.
Meski saya membuat pengelompokan tersebut, bukan berarti kelompok pertama akan lebih unggul dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini masih sangat tergantung bagaimana dinamika politik tujuh bulan mendatang. Namun jika indikasi yang diambil adalah hingga saat ini, nama Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid, Wiranto dan Prabowo masih menjadi kandidat paling baik. Keempatnya memiliki 4 kriteria yang wajib dimiliki oleh wakil presiden, yakni popularitas, kendaraan politik, dana kampanye dan pengalaman birokratik yang baik. Namun tak menutup kemungkinan juga calon lain bisa muncul menjadi rising star seperti Sarah Palin yang tak diperhitungkan sebelumnya.
Baca Selengkapnya...
Koran Sindo
 UU Pilpres belum selesai hingga kini. Masalah kapan pejabat negara harus mengundurkan diri jika menjadi capres/cawapres, masalah rangkap jabatan serta persoalan ambang batas perolehan suara partai untuk mengajukan capres/cawapres masih menjadi kendala. Meski begitu, ada satu kesimpulan awal yang bisa dihadirkan terhadap UU Pilpres yang akan diundangkan, yakni pemilu 2009 mendatang tampaknya akan sulit menghadirkan calon presiden muka baru. Konstelasi tetap akan diramaikan oleh wajah lama seperti SBY, Megawati, Amin Rais, Wiranto serta tokoh-tokoh ”tua” lainnya. Dan pertarungan pun sepertinya akan mengerucut pada sosok SBY dan Megawati. Karena hingga kini, hanya kedua tokoh itulah yang paling populer memenangkan pilihan presiden berdasarkan hasil berbagai lembaga survei.
UU Pilpres belum selesai hingga kini. Masalah kapan pejabat negara harus mengundurkan diri jika menjadi capres/cawapres, masalah rangkap jabatan serta persoalan ambang batas perolehan suara partai untuk mengajukan capres/cawapres masih menjadi kendala. Meski begitu, ada satu kesimpulan awal yang bisa dihadirkan terhadap UU Pilpres yang akan diundangkan, yakni pemilu 2009 mendatang tampaknya akan sulit menghadirkan calon presiden muka baru. Konstelasi tetap akan diramaikan oleh wajah lama seperti SBY, Megawati, Amin Rais, Wiranto serta tokoh-tokoh ”tua” lainnya. Dan pertarungan pun sepertinya akan mengerucut pada sosok SBY dan Megawati. Karena hingga kini, hanya kedua tokoh itulah yang paling populer memenangkan pilihan presiden berdasarkan hasil berbagai lembaga survei.Melihat kondisi di atas, menjadi cukup menarik apabila kemudian memfokuskan perhatian terhadap pasangan yang akan mendampingi mereka. Karena posisi wakil presiden adalah kartu truf. Ibarat dua mata pisau, posisinya bisa mengangkat pun bisa juga menjatuhkan. Kita mungkin bisa sedikit berkaca dari pemilu AS yang kini sedang berlangsung. Jauh hari ketika Obama dan Maccain masih berjuang memenangkan konvensi dipartai masing-masing, Obama selalu unggul diberbagai hasil jajak pendapat. Namun setelah Maccain menggandeng Sarah Palin dan Obama menggamit Joe Biden, konstelasi langsung berubah. Obama kini tertinggal, meski tak drastis. Artinya, unsur Sarah Palin bisa mengangkat popularitas Maccain dan Joe Biden tak terlalu berpengaruh terhadap popularitas Obama. Bagaimana dengan Indonesia? Siapa wapres yang berpotensi mengangkat pasangannya pada pemilu 2009 mendatang?
Dalam memilih pasangan, hemat saya, seorang calon presiden akan memperhatikan dua aspek pokok. Pertama, wakil yang akan dipilih harus bisa membantu untuk memenangkan general election, karena itu tujuan utama. Namun hal kedua yang tak kalah penting adalah, pasangan tersebut harus bisa mendampingi sang presiden dalam hal apapun ketika mereka telah terpilih.
Dalam konteks mencari calon wakil presiden ideal yang memenuhi dua kriteria di atas, setidak-tidaknya capres harus memperhatikan filosofi lima jari. Pertama, wakil yang dipilih harus seperti jempol. Artinya pasangan yang akan digamit harus hebat. Hebat disini diartikan mempunyai bibit, bebet dan bobot yang baik. Bibit berarti ia harus berasal dari partai yang kuat guna mendukung kebijakan-kebijakan di parlemen. Ia juga harus populer sehingga dapat membantu mengangkat popularitas pasangannya dan mempunyai dana yang cukup untuk kampanye. Bebet berarti ia mempunyai lingkungan yang loyal atau dalam bahasa lain mempunyai basis konstituen yang fanatik. Bobot diartikan harus memiliki nilai pribadi yang handal seperti attitude yang baik, pengetahuan yang luas dan konsep pengendalian diri yang mumpuni.
Kriteria jari selanjutnya dalam mencari wakil, ia harus bisa seperti kelingking. Arti kelingking disini adalah ia harus dapat menjadi negasi. Ia harus berani mendebat keputusan yang dianggap menyimpang. Meski begitu, sang wakil harus tetap rendah hati untuk bisa menemukan sintesis yang baik. Karena jika tak rendah hati seperti kelingking, pasangan tersebut bisa bubar ditengah jalan.
Ketiga, pasangan yang akan digamit juga harus bisa seperti jari telunjuk. Ia bisa membimbing dan menjadi guide yang profesional. Ia tak hanya mendebat, melainkan dapat menunjukkan jalan alternatif bagi perjalanan keduanya. Keempat, ia harus bisa menjadi seperti jari manis. Artinya ia mau berkomitmen untuk saling menerima kekurangan masing-masing. Implikasinya, keduanya akan menjadi pasangan yang understanding dan saling melengkapi cela kelemahan yang ada. Ujungnya, ia tak akan jalan sendiri-sendiri yang bermuara pada ”perceraian”.
Kelima, wakil yang dipilih harus menjadi seperti jari tengah. Artinya, pasangan harus berkomitmen mendahulukan persoalan pasangan dan menjaga agar pasangan tersebut bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan selama 5 tahun kedepan. Keduanya akan saling berkomitmen menyelesaikan persoalan mereka terlebih dahulu sebelum lari ke masalah negara yang lebih luas. Harapannya, keduanya akan selalu harmonis dalam meregulasi kehidupan negara yang sangat berat.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kira-kira siapa cawapres Indonesia yang bisa memenuhi kriteria-kriteria diatas?
JK, Hidayat, Wiranto dan Prabowo
Kala survei dilakukan untuk mengetahui nama-nama potensial untuk kedudukan sebagai calon wakil presiden, nama yang beredar di bursa memang lebih beragam dibandingkan dengan kandidat calon presiden. Survei Indo Barometer pada Juni 2008 menunjukkan hal itu. Dalam pertanyaan terbuka untuk nama cawapres, ada 10 nama muncul dengan dukungan suara terbanyak. Mereka adalah Sri Sultan HB X (19,9%), Jusuf Kalla (12,3%), Hidayat Nur Wahid (10,7%), Yusril Ihza Mahendra (4,9%); Prabowo Subianto (4,9%), Akbar Tanjung (4,6%), Hasyim Muzadi(4%), Din Syamsuddin (3,3%), Agung Laksono (2,8%) dan Aburizal Bakrie (2,2%). Dan sebetulnya masih banyak lagi nama lainnya. Lantas, siapa diantara mereka yang paling potensial?
Jika merujuk kriteria filosofi lima jari yang telah tertera sebelumnya, tentu tak semua nama di atas masuk kategori potensial. Hemat saya, tingkatan potensial bisa dibuat dalam kelompok-kelompok bertangga. Kelompok pertama ada nama Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid, Wiranto, Yusril Ihza Mahendra dan Prabowo. Kelompok kedua ada nama Sultan HB X dan Akbar Tandjung. Serta kelompok ketiga adalah nama-nama lainnya. atas dasar apa pengeleompokan itu?
Kelompok pertama dimasukkan dengan indikator, nama-nama itu memenuhi 4 unsur utama, yakni mempunyai kendaraan politik cukup potensial pada pemilu 2009 mendatang dan kans untuk menjadi presiden masih diragukan. Selain kendaraan politik, dana untuk berkampanye juga tak menjadi persoalan bagi kelompok pertama ini. Dalam hal popuaritas, kelompok ini juga cukup menjanjikan bisa mengatrol pasangannya. Dalam hal pengetahuan dan pengalaman memimpin, kelompok pertama ini telah mengenyam banyak pengalaman di birokrasi.
Dibawah kelompok pertama ini ada nama Sultan HB X dan Akbar Tandjung. Kenapa dua nama ini masuk kelompok kedua? Padahal popularitas HB X malah yang tertinggi diantara cawapres lainnya? Hemat saya, hal ini lantaran keduanya hingga kini belum mau secara tegas berafiliasi dengan salah satu partai yang ada. Padahal, syarat mutlak untuk mendapatkan tempat wakil presiden adalah koalisi untuk share kekuasaan. Dan jika keduanya hingga beberapa waktu kedepan tak menentukan kendaraan politik, rasanya cukup sulit untuk bisa digandeng capres yang telah mapan. Karena mereka tak mungkin lagi mendapat dukungan dari Golkar yang sudah pasti akan mengusung ketua umum mereka, Jusuf Kalla.
Kelompok paling akhir adalah nama-nama yang saat ini sedang sibuk mengiklankan diri atau bahkan nama yang belum muncul sama sekali. Sebut saja Sutrisno Bachir, Rizal Mallarangeng, Fajroel Rahman dll. Kenapa nama-nama ini? Itu tak lain karena mereka dalam hal popularitas masih sangat minim. Yang menjadi catatan lagi, sosok Sutrisno Bachir, meski iklan di media massa sangat gencar, tapi penilaian publik masih cukup rendah. Hal ini karena ia belum begitu konkrit menunjukkan peran-aktif ditengah-tengah masyarakat.
Meski saya membuat pengelompokan tersebut, bukan berarti kelompok pertama akan lebih unggul dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini masih sangat tergantung bagaimana dinamika politik tujuh bulan mendatang. Namun jika indikasi yang diambil adalah hingga saat ini, nama Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid, Wiranto dan Prabowo masih menjadi kandidat paling baik. Keempatnya memiliki 4 kriteria yang wajib dimiliki oleh wakil presiden, yakni popularitas, kendaraan politik, dana kampanye dan pengalaman birokratik yang baik. Namun tak menutup kemungkinan juga calon lain bisa muncul menjadi rising star seperti Sarah Palin yang tak diperhitungkan sebelumnya.