Oleh: Abdul Hakim MS.
Harian Umum Pelita, 23 Juli 2008
Pada 7 Juli 2008, babak baru sejarah perpolitikan Indonesia kembali tergores. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundangkan 34 partai politik nasional (dan 6 partai lokal di Aceh) sebagai peserta pemilu legislatif 9 April 2009. Jumlah ini tentu (tak) mengejutkan. Ekpektasi besar yang digadang untuk membentuk sistem kepartaian yang efektif (multi-partai sederhana) guna mendukung sistem presidensil, pupus. Kita kembali lagi kesiklus sistem kepartaian multi-partai ekstrim, meski jumlahnya tak sebanyak seperti pada pemilu 1955.
Euforia demokrasi kita memang belum berhenti. Pada 1955, jumlah parpol yang ikut pemilu sempat mencapai jumlah 172 partai. Pada 1971, menciut menjadi 10 partai. Pada 1977-1997, dengan paksaan melakukan fusi oleh pemerintah Orde Baru, partai politik peserta pemilu mewujud menjadi hanya 3 saja.
Namun setelah era reformasi menjelang, kembali semarak mendirikan partai yang sempat terbendung, membuncah. Pemilu 1999 diikuti 48 partai. Lima tahun berikutnya, menyempit menjadi 24 partai. Dan pada pemilu 2009 mendatang, sekali lagi, surat suara akan disesaki oleh gambar 34 partai yang berbeda. Apa implikasinya?
Potensi Golput Tinggi
Banyaknya jumlah parpol yang ada, secara eufinis mungkin bisa diinterpretasikan sebagai bentuk keragaman negeri ini. Namun ada pandangan skeptis bahwa lahirnya banyak parpol akhir-akhir ini, hanya dilandasi oleh kehausan elit memperoleh kekuasaan. Skeptisisme ini muncul, lantaran petinggi-petinggi parpol baru, masih didominasi oleh sempalan kader-kader partai lama. Sebut saja Wiranto dengan Hanura-nya, Prabowo dengan Gerindra-nya dan seterusnya.
Jika merujuk pada hasil survei, sikap skeptisisme ini seoalah mendapatkan legitimasi. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis data, bahwa Jauh lebih sedikit dari publik yang yakin bahwa partai politik mewakili keinginan pemilih. Angkanya juga cukup tinggi, 72,9%. Publik begitu yakin bahwa parpol hanya memperjuangkan segelintir kelompok kecil.
Disamping itu, publik juga tak mampu membedakan parpol dalam tataran visi-misi dan program kerja yang jelas karena jumlahnya cukup banyak. Survei Indo Barometer (IB) pada Juni 2008 menyebut, 88,2% publik menyatakan jumlah partai politik saat ini terlalu banyak. Publik menjadi bingung. Dan kalau sudah begitu, banyak diantara mereka yang menginginkan untuk tidak memilih pada pemilu 2009 mendatang (golput).
Indikasi naiknya golput pada pemilu 2009, sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak dini. Selain faktor di atas, kala kita mengacu sejarah kepemiluan Indonesia, dari Pemilu 1971 hingga ke Pemilu 2004, tren persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya kian menyusut. Ironisnya, titik penurunan itu terjadi saat demokrasi dan kebebasan sangat terbuka, Pemilu 1999 dan 2004. Pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya naik menjadi 7,2 persen dibandingkan Pemilu 1997 yang hanya 6,4 persen saja.
Lebih parah, penurunan partisipasi itu terjadi pada Pemilu 2004 lalu. Dalam tiga rangakaian pemilu yang diselenggarakan secara berurutan kala itu, sebanyak 16 persen dari pemilih terdaftar tidak menyumbangkan suaranya untuk pemilu legislatif. Kemudian, angka ini mengalami kenaikan menjadi 21,77 persen pada pilpres putaran pertama. Angka ini kembali naik pada pilpres putaran kedua menjadi 23,37 persen. Padahal, dalam Pemilu 2004, sistem pemilu sudah berubah menjadi pemilihan secara langsung dan euforia demokrasi sedang marak-maraknya.
Untuk pemilu 2009, sepertinya kita tak banyak bisa berharap. Selain kejengahan masyarakat terhadap sepak-terjang partai politik, publik juga telah pandai menganalisa mana partai yang benar memberikan manfaat pada mereka dan mana partai yang hanya menjadi ”pecundang”.
Tentu Indikasi ini tak begitu baik bagi perkembangan demokrasi kita. Institusi publik yang dipilih melalui lembaga pemilu, menjadi tereduksi legitimasinya, baik legislatif maupun eksekutif.
Borgol Presiden
Implikasi lain yang hadir tatkala jumlah partai politik mewabah, adalah kesulitan eksekutif melakukan konsolidasi pemerintahan. Seperti kita tahu, sistem pemerintahan kita saat ini adalah presidensialisme. Sistem presidensial, bisa berjalan efektif apabila didukung oleh sistem kepartaian multipartai sederhana. Saat ini, sistem kepartaian kita multi partai ekstrim dengan jumlah peserta pemilu mencapai 34 partai politik.
Coba kita berandai-andai hasil pemilu 2009 berdasarkan hasil survei Indo Barometer (IB) pada Juni 2008. Kira-kira bagaimana susunan kabinetnya dan apa persoalan utama yang dihadapi oleh presiden.
Berdasarkan data Indo Barometer Juni 2008, PDIP memenangkan pemilu legislatif dengan 23%. Sedangkan pemenang pemilihan presiden juga digamit oleh Megawati dengan 30,9%. Jika kondisi ini yang terjadi, PDIP dan Megawati bisa menghasilkan unified government (pemerintahan yang satu) karena pemenang pemilu legislatif dan presiden berasal dari partai yang sama. Namun, kondisi ini tak menjamin pemerintahan Mega bisa berjalan efektif. Karena di DPR, 77% kekuatan diisi oleh partai lain. Mau tak mau, Mega tetap harus mengakomodasi kekuatan besar ini, sehingga kabinetnya akan menjadi pelangi. Kondisi ini tentu menjadi ”borgol” tersendiri bagi Ketua Umum PDIP ini. Berdasarkan pengalaman, menteri yang notabene berasal dari perwakilan partai politik DPR, kerap berbuat dualisme. Satu sisi membela kebijakan pemerintah, namun di DPR, partainya mengkritik habis kebijakan yang telah disepakati.
Skenario kedua, pemilu legislatif dimenangkan oleh PDIP dengan 23% dan pemilihan presiden dimenangkan SBY. Skenario ini terjadi bila PDIP survive sebagai parpol pemenang pemilu 2009 dan SBY berhasil memulihkan popularitas dirinya yang sekarang anjlok. Meskipun sekarang mungkin lebih berat, data survei tahun 2005-2006 menunjukkan SBY pernah melakukan ”recovery” popularitas dirinya. Pasca kenaikan BBM tahun 2005, kepuasan terhadap pemerintahan SBY turun. Namun bisa merangkak naik kembali pada tahun 2006.
Jika hal ini yang terjadi, SBY tetap seperti posisinya sekarang. Kesulitan mengendalikan kabinetnya karena ia harus membentuknya dari komposisi berbagai macam parpol. Dan jika kabinetnya bentuknya seperti ini, situasi pemerintahan 2004-2009 kembali akan terulang. SBY akan dikepung dualisme kepentingan pembantunya, sebagai bawahan dan juga sebagai politisi partai.
Kondisi yang sama juga akan terjadi apabila pemenang pemilihan presiden digenggam oleh kandidat lain, misalnya Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, Sultan HB X atau siapa saja, sedangkan pemenang pemilu di rengkuh PDIP atau Golkar. Mereka akan tetap dihadapkan pada biasnya kekuatan parpol di DPR, yang secara tidak langsung akan membuat sulit presiden untuk mengeluarkan kebijakan secara sempurna. Jika kondisinya seperti ini, siapapun presiden yang terpilih pada pemilu 2009, jurang terjal telah menghadang didepan mata.
Masihkan kita optimis dengan hasil pemilu 2009 untuk menyembulkan pemimpin yang bisa membawa kita keluar dari multikrisis yang masih mendera bangsa ini hingga kini? Biarlah waktu yang menjawab.
Harian Umum Pelita, 23 Juli 2008
Pada 7 Juli 2008, babak baru sejarah perpolitikan Indonesia kembali tergores. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundangkan 34 partai politik nasional (dan 6 partai lokal di Aceh) sebagai peserta pemilu legislatif 9 April 2009. Jumlah ini tentu (tak) mengejutkan. Ekpektasi besar yang digadang untuk membentuk sistem kepartaian yang efektif (multi-partai sederhana) guna mendukung sistem presidensil, pupus. Kita kembali lagi kesiklus sistem kepartaian multi-partai ekstrim, meski jumlahnya tak sebanyak seperti pada pemilu 1955.
Euforia demokrasi kita memang belum berhenti. Pada 1955, jumlah parpol yang ikut pemilu sempat mencapai jumlah 172 partai. Pada 1971, menciut menjadi 10 partai. Pada 1977-1997, dengan paksaan melakukan fusi oleh pemerintah Orde Baru, partai politik peserta pemilu mewujud menjadi hanya 3 saja.
Namun setelah era reformasi menjelang, kembali semarak mendirikan partai yang sempat terbendung, membuncah. Pemilu 1999 diikuti 48 partai. Lima tahun berikutnya, menyempit menjadi 24 partai. Dan pada pemilu 2009 mendatang, sekali lagi, surat suara akan disesaki oleh gambar 34 partai yang berbeda. Apa implikasinya?
Potensi Golput Tinggi
Banyaknya jumlah parpol yang ada, secara eufinis mungkin bisa diinterpretasikan sebagai bentuk keragaman negeri ini. Namun ada pandangan skeptis bahwa lahirnya banyak parpol akhir-akhir ini, hanya dilandasi oleh kehausan elit memperoleh kekuasaan. Skeptisisme ini muncul, lantaran petinggi-petinggi parpol baru, masih didominasi oleh sempalan kader-kader partai lama. Sebut saja Wiranto dengan Hanura-nya, Prabowo dengan Gerindra-nya dan seterusnya.
Jika merujuk pada hasil survei, sikap skeptisisme ini seoalah mendapatkan legitimasi. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis data, bahwa Jauh lebih sedikit dari publik yang yakin bahwa partai politik mewakili keinginan pemilih. Angkanya juga cukup tinggi, 72,9%. Publik begitu yakin bahwa parpol hanya memperjuangkan segelintir kelompok kecil.
Disamping itu, publik juga tak mampu membedakan parpol dalam tataran visi-misi dan program kerja yang jelas karena jumlahnya cukup banyak. Survei Indo Barometer (IB) pada Juni 2008 menyebut, 88,2% publik menyatakan jumlah partai politik saat ini terlalu banyak. Publik menjadi bingung. Dan kalau sudah begitu, banyak diantara mereka yang menginginkan untuk tidak memilih pada pemilu 2009 mendatang (golput).
Indikasi naiknya golput pada pemilu 2009, sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak dini. Selain faktor di atas, kala kita mengacu sejarah kepemiluan Indonesia, dari Pemilu 1971 hingga ke Pemilu 2004, tren persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya kian menyusut. Ironisnya, titik penurunan itu terjadi saat demokrasi dan kebebasan sangat terbuka, Pemilu 1999 dan 2004. Pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya naik menjadi 7,2 persen dibandingkan Pemilu 1997 yang hanya 6,4 persen saja.
Lebih parah, penurunan partisipasi itu terjadi pada Pemilu 2004 lalu. Dalam tiga rangakaian pemilu yang diselenggarakan secara berurutan kala itu, sebanyak 16 persen dari pemilih terdaftar tidak menyumbangkan suaranya untuk pemilu legislatif. Kemudian, angka ini mengalami kenaikan menjadi 21,77 persen pada pilpres putaran pertama. Angka ini kembali naik pada pilpres putaran kedua menjadi 23,37 persen. Padahal, dalam Pemilu 2004, sistem pemilu sudah berubah menjadi pemilihan secara langsung dan euforia demokrasi sedang marak-maraknya.
Untuk pemilu 2009, sepertinya kita tak banyak bisa berharap. Selain kejengahan masyarakat terhadap sepak-terjang partai politik, publik juga telah pandai menganalisa mana partai yang benar memberikan manfaat pada mereka dan mana partai yang hanya menjadi ”pecundang”.
Tentu Indikasi ini tak begitu baik bagi perkembangan demokrasi kita. Institusi publik yang dipilih melalui lembaga pemilu, menjadi tereduksi legitimasinya, baik legislatif maupun eksekutif.
Borgol Presiden
Implikasi lain yang hadir tatkala jumlah partai politik mewabah, adalah kesulitan eksekutif melakukan konsolidasi pemerintahan. Seperti kita tahu, sistem pemerintahan kita saat ini adalah presidensialisme. Sistem presidensial, bisa berjalan efektif apabila didukung oleh sistem kepartaian multipartai sederhana. Saat ini, sistem kepartaian kita multi partai ekstrim dengan jumlah peserta pemilu mencapai 34 partai politik.
Coba kita berandai-andai hasil pemilu 2009 berdasarkan hasil survei Indo Barometer (IB) pada Juni 2008. Kira-kira bagaimana susunan kabinetnya dan apa persoalan utama yang dihadapi oleh presiden.
Berdasarkan data Indo Barometer Juni 2008, PDIP memenangkan pemilu legislatif dengan 23%. Sedangkan pemenang pemilihan presiden juga digamit oleh Megawati dengan 30,9%. Jika kondisi ini yang terjadi, PDIP dan Megawati bisa menghasilkan unified government (pemerintahan yang satu) karena pemenang pemilu legislatif dan presiden berasal dari partai yang sama. Namun, kondisi ini tak menjamin pemerintahan Mega bisa berjalan efektif. Karena di DPR, 77% kekuatan diisi oleh partai lain. Mau tak mau, Mega tetap harus mengakomodasi kekuatan besar ini, sehingga kabinetnya akan menjadi pelangi. Kondisi ini tentu menjadi ”borgol” tersendiri bagi Ketua Umum PDIP ini. Berdasarkan pengalaman, menteri yang notabene berasal dari perwakilan partai politik DPR, kerap berbuat dualisme. Satu sisi membela kebijakan pemerintah, namun di DPR, partainya mengkritik habis kebijakan yang telah disepakati.
Skenario kedua, pemilu legislatif dimenangkan oleh PDIP dengan 23% dan pemilihan presiden dimenangkan SBY. Skenario ini terjadi bila PDIP survive sebagai parpol pemenang pemilu 2009 dan SBY berhasil memulihkan popularitas dirinya yang sekarang anjlok. Meskipun sekarang mungkin lebih berat, data survei tahun 2005-2006 menunjukkan SBY pernah melakukan ”recovery” popularitas dirinya. Pasca kenaikan BBM tahun 2005, kepuasan terhadap pemerintahan SBY turun. Namun bisa merangkak naik kembali pada tahun 2006.
Jika hal ini yang terjadi, SBY tetap seperti posisinya sekarang. Kesulitan mengendalikan kabinetnya karena ia harus membentuknya dari komposisi berbagai macam parpol. Dan jika kabinetnya bentuknya seperti ini, situasi pemerintahan 2004-2009 kembali akan terulang. SBY akan dikepung dualisme kepentingan pembantunya, sebagai bawahan dan juga sebagai politisi partai.
Kondisi yang sama juga akan terjadi apabila pemenang pemilihan presiden digenggam oleh kandidat lain, misalnya Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, Sultan HB X atau siapa saja, sedangkan pemenang pemilu di rengkuh PDIP atau Golkar. Mereka akan tetap dihadapkan pada biasnya kekuatan parpol di DPR, yang secara tidak langsung akan membuat sulit presiden untuk mengeluarkan kebijakan secara sempurna. Jika kondisinya seperti ini, siapapun presiden yang terpilih pada pemilu 2009, jurang terjal telah menghadang didepan mata.
Masihkan kita optimis dengan hasil pemilu 2009 untuk menyembulkan pemimpin yang bisa membawa kita keluar dari multikrisis yang masih mendera bangsa ini hingga kini? Biarlah waktu yang menjawab.







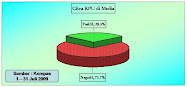
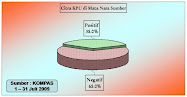
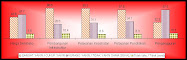


No comments:
Post a Comment