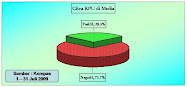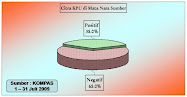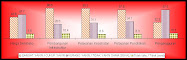Oleh : Abdul Hakim MS.

Apa yang paling fenomenal dari pemilu 2004? Hemat saya, sedikitnya ada tiga hal utama. Pertama, meyembulnya fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD). Kedua, fenomena pelaksanaan pemilu yang oleh berbagai pihak dipandang sebagai pesta demokrasi paling demokratis selain Pemilu 1999 dan 1955. Ketiga, fenomena lahirnya prediksi hasil pemilu yang akuratif melalui survei politik. Dari ketiga fenomena di atas, lahirnya prediksi akuratif melalui metodologi survei politik, adalah hal yang paling menarik untuk dicermati. Kala itu, survei politik merupakan mahluk baru dipentas perpolitikan nasional. Awal kehadirannya mencengangkan berbagai kalangan. Banyak yang apreseatif, pun tak sedikit yang apriori.
Kini, pro-kontra sekitar hasil survei kembali diperdebatkan. Dipicu oleh prediksi beberapa lembaga survei yang berbeda terhadap hasil akhir Pilkada Provinsi Sumatera Selatan melalui penghitungan cepat (quick count), menyembulkan keprihatinan terhadap lembaga survei yang bermunculan. Ujungnya, ada dorongan agar lembaga-lembaga survei itu disertifikasi agar kredibilatsnya terjamin dan tak hanya menjadi alat politik kelompok tertentu.
Seperti kita tahu, beberapa jam setelah pencoblosan di Pilkada Sumsel pada 4 September 2008 lalu, tiga lembaga survei melakukan prediksi cepat (quick count). Pusat Kajian Pembangunan Strategis (Puskaptis) memprediksi kemenangan pasangan Syahrial Oesman-Helmy Yahya dengan 51,11 persen atas pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf yang memperoleh 48,89 persen. Berbeda dengan Puskaptis, hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan Alex-Eddy menang atas Syahrial-Helmy dengan jumlah dukungan 52,12 persen berbanding 47,88 persen. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pun memenangkan pasangan Alex-Eddy atas Syahrial-Helmy dengan perolehan suara 51 persen berbanding 49 persen. Hasil faktual yang diumumkan oleh KPUD Sumsel, ternyata memenangkan pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf dengan 51,40 persen atas pasangan Syahrial Oesman-Helmy Yahya yang meraih 48,60 persen.
Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa prediksi satu lembaga survei bisa berbeda dengan lembaga survei lainnya?
Tes Darah
Sebetulnya, kesalahan prediksi dalam survei politik merupakan hal biasa. Itu dikarenakan survei politik juga dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, kesalahan prediksi sebenarnya dapat diminimalisasi apabila metodologi survei politik yang dijalankan telah memenuhi kaidah-kaidah standar ilmiah yang telah ditetapkan. Berbeda metodologi, pasti berbeda pula hasil yang akan didapatkan.
Analogi sederhana untuk menggambarkan survei politik, ibarat dokter yang akan melakukan tes penyakit terhadap pasiennya. Untuk memastikan pasien terjangkit penyakit apa, dokter biasanya akan melakukan tes darah. Pertanyaannya, apakah sidokter akan mengambil semua darah yang ada ditubuh pasien untuk melakukan tes? Tentu tidak. Dokter hanya memerlukan setetes darah sebagai sampel untuk diuji dilaboratorium. Nah, persoalan utama adalah, dengan metode apa dokter menguji darah itu? Apakah dengan alat-alat yang sudah baku didunia kedokteran atau dengan metode yang lain? Jika dokter menggunakan metode yang benar, pasti hasilnya akan dapat menggambarkan jenis penyakit apa yang diderita si pasien. Dengan darah setetes, bisa mengetahui kondisi badan secara keseluruhan.
Begitu pula dengan survei politik. Untuk mengetahui persepsi publik Indonesia tentang suatu persoalan, misalnya, apakah harus menanyakan persoalan itu kepada 220 juta penduduk Indonesia? Sudah pasti tidak. Survei politik hanya memerlukan, misalnya 1200 responden yang diambil guna dijadikan sampel. Dari 1200 responden ini kemudian diolah dan dites sesuai dengan metodologi ilmiah. Jika metode yang digunakan tepat, maka jumlah 1200 responden itu dapat mewakili suara 220 juta lebih warga Indonesia. Sebaliknya, apabila metodologi yang digunakan untuk menguji 1200 responden itu salah, tentu hasilnya tak bisa dijadikan cermin atas suara seluruh penduduk Indonesia. Disinilah penjelasan kenapa prediksi satu lembaga survei bisa berbeda dengan lembaga survei lainnya. Intinya terletak pada bagaimana lembaga tersebut mengelola sampel dengan baik sesuai dengan prosedur akademis.
Seleksi Alamiah
Hadirnya survei politik dalam kancah politik nasional, memang ibarat dua sisi mata pedang. Satu sisi, keberadaannya merupakan perkembangan sangat baik bagi demokrasi kita. Ia sangat membantu mengetahui persoalan sosial-kemasyarakatan dengan cepat dan akurat. Namun disisi lain, keberadaannya juga sangat meresahkan. Itu tak lain apabila data yang dimunculkan tak benar dan menyesatkan. Apalagi, kalau survei politik yang dilakukan hanya bertujuan untuk kepentingan politik semata dengan menerabas pakem metodologi, kemudian hasilnya dipublikasikan kemasyarakat. Disinilah persoalan utama yang menjadi PR lembaga-lembaga survei.
Sudah menjadi rahasia umum, seiring dengan makin percayanya masyarakat terhadap prediksi hasil survei politik, muncul seabreg nama lembaga survei politik baru. Saat ini jumlahnya puluhan. Ada yang hadir karena memang benar-benar ingin memotret dan menunjukkan realitas politik kepada masyarakat dengan metodologi yang semestinya. Akan tetapi tak sedikit yang menyembul hanya ingin mempengaruhi opini massa melalui teori bandwagon effect atau underdog effect. Disinilah yang berbahaya. Jika alasan pendiriannya demikian, maka pakem metodologi akan diterabas dan hasilnya diolah sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga survei bersangkutan.
Berdasarkan kondisi di atas, maka tak mengherankan apabila muncul wacana sertifikasi lembaga survei. Tujuannya baik, untuk membedakan mana lembaga survei yang kredibel dan mana lembaga survei yang abal-abal. Namun siapa yang akan memberikan sertifikat? Apakah pemerintah, organisasi profesi atau siapa?
Sertifikasi memang penting selama lembaga yang akan memberikan sertifikat adalah lembaga yang benar-benar kredibel. Namun, jika yang memberi sertifikat adalah pemerintah, saya ragu. Proses intervensi akan tinggi. Bisa juga, sertifikat dijadikan alat kontrol kepada lembaga survei dengan tujuan politis. Sama halnya dengan SIUPP untuk menerbitkan surat kabar pada zaman Orba. Atau sertifikat diberikan oleh organisasi profesi? seperti AROPI misalnya. Hal ini juga tak menyelesaikan persoalan. Karena tak semua lembaga survei menjadi anggota organisasi profesi tersebut.
Akan lebih baik apabila proses muncul dan matinya lembaga survei ini diserahkan kepada masyarakat. Jika satu lembaga survei memang kredibel, maka dengan sendirinya ia akan tetap eksis. Dan bagi lembaga survei abal-abal, masyarakat saat ini sudah sangat pintar menganalisa. Biarkan vonis masyarakat yang menentukan. Namun yang tak kalah penting adalah peran media massa. Harus ada semacam punishment terhadap lembaga survei yang ”bermain nakal” apabila telah terkait dengan urusan publik. Media massa mempunyai tanggung jawab juga atas apa yang dipublikasikan kemasyarakat dengan mengutip data dari lembaga survei. Oleh karena itu, media harus selektif dalam menurunkan data hasil survei. Jika data lembaga survei tertentu kerap menyimpang dengan hasil faktual, tak semestinya datanya menjadi referensi. Akan tetapi jika data sebuah lembaga survei terbuktif akurat, sudah sewajarnya media menjadikan data lembaga itu sebagai rujukan. Dengan begitu, lembaga survei akan terseleksi dengan sendirinya. Yang pasti, demokrasi kita saat ini sangat membutuhkan instrumen survei politik guna memotret keadaan sosial-kemasyarakat teranyar.
Baca Selengkapnya...

Apa yang paling fenomenal dari pemilu 2004? Hemat saya, sedikitnya ada tiga hal utama. Pertama, meyembulnya fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD). Kedua, fenomena pelaksanaan pemilu yang oleh berbagai pihak dipandang sebagai pesta demokrasi paling demokratis selain Pemilu 1999 dan 1955. Ketiga, fenomena lahirnya prediksi hasil pemilu yang akuratif melalui survei politik. Dari ketiga fenomena di atas, lahirnya prediksi akuratif melalui metodologi survei politik, adalah hal yang paling menarik untuk dicermati. Kala itu, survei politik merupakan mahluk baru dipentas perpolitikan nasional. Awal kehadirannya mencengangkan berbagai kalangan. Banyak yang apreseatif, pun tak sedikit yang apriori.
Kini, pro-kontra sekitar hasil survei kembali diperdebatkan. Dipicu oleh prediksi beberapa lembaga survei yang berbeda terhadap hasil akhir Pilkada Provinsi Sumatera Selatan melalui penghitungan cepat (quick count), menyembulkan keprihatinan terhadap lembaga survei yang bermunculan. Ujungnya, ada dorongan agar lembaga-lembaga survei itu disertifikasi agar kredibilatsnya terjamin dan tak hanya menjadi alat politik kelompok tertentu.
Seperti kita tahu, beberapa jam setelah pencoblosan di Pilkada Sumsel pada 4 September 2008 lalu, tiga lembaga survei melakukan prediksi cepat (quick count). Pusat Kajian Pembangunan Strategis (Puskaptis) memprediksi kemenangan pasangan Syahrial Oesman-Helmy Yahya dengan 51,11 persen atas pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf yang memperoleh 48,89 persen. Berbeda dengan Puskaptis, hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan Alex-Eddy menang atas Syahrial-Helmy dengan jumlah dukungan 52,12 persen berbanding 47,88 persen. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pun memenangkan pasangan Alex-Eddy atas Syahrial-Helmy dengan perolehan suara 51 persen berbanding 49 persen. Hasil faktual yang diumumkan oleh KPUD Sumsel, ternyata memenangkan pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf dengan 51,40 persen atas pasangan Syahrial Oesman-Helmy Yahya yang meraih 48,60 persen.
Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa prediksi satu lembaga survei bisa berbeda dengan lembaga survei lainnya?
Tes Darah
Sebetulnya, kesalahan prediksi dalam survei politik merupakan hal biasa. Itu dikarenakan survei politik juga dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, kesalahan prediksi sebenarnya dapat diminimalisasi apabila metodologi survei politik yang dijalankan telah memenuhi kaidah-kaidah standar ilmiah yang telah ditetapkan. Berbeda metodologi, pasti berbeda pula hasil yang akan didapatkan.
Analogi sederhana untuk menggambarkan survei politik, ibarat dokter yang akan melakukan tes penyakit terhadap pasiennya. Untuk memastikan pasien terjangkit penyakit apa, dokter biasanya akan melakukan tes darah. Pertanyaannya, apakah sidokter akan mengambil semua darah yang ada ditubuh pasien untuk melakukan tes? Tentu tidak. Dokter hanya memerlukan setetes darah sebagai sampel untuk diuji dilaboratorium. Nah, persoalan utama adalah, dengan metode apa dokter menguji darah itu? Apakah dengan alat-alat yang sudah baku didunia kedokteran atau dengan metode yang lain? Jika dokter menggunakan metode yang benar, pasti hasilnya akan dapat menggambarkan jenis penyakit apa yang diderita si pasien. Dengan darah setetes, bisa mengetahui kondisi badan secara keseluruhan.
Begitu pula dengan survei politik. Untuk mengetahui persepsi publik Indonesia tentang suatu persoalan, misalnya, apakah harus menanyakan persoalan itu kepada 220 juta penduduk Indonesia? Sudah pasti tidak. Survei politik hanya memerlukan, misalnya 1200 responden yang diambil guna dijadikan sampel. Dari 1200 responden ini kemudian diolah dan dites sesuai dengan metodologi ilmiah. Jika metode yang digunakan tepat, maka jumlah 1200 responden itu dapat mewakili suara 220 juta lebih warga Indonesia. Sebaliknya, apabila metodologi yang digunakan untuk menguji 1200 responden itu salah, tentu hasilnya tak bisa dijadikan cermin atas suara seluruh penduduk Indonesia. Disinilah penjelasan kenapa prediksi satu lembaga survei bisa berbeda dengan lembaga survei lainnya. Intinya terletak pada bagaimana lembaga tersebut mengelola sampel dengan baik sesuai dengan prosedur akademis.
Seleksi Alamiah
Hadirnya survei politik dalam kancah politik nasional, memang ibarat dua sisi mata pedang. Satu sisi, keberadaannya merupakan perkembangan sangat baik bagi demokrasi kita. Ia sangat membantu mengetahui persoalan sosial-kemasyarakatan dengan cepat dan akurat. Namun disisi lain, keberadaannya juga sangat meresahkan. Itu tak lain apabila data yang dimunculkan tak benar dan menyesatkan. Apalagi, kalau survei politik yang dilakukan hanya bertujuan untuk kepentingan politik semata dengan menerabas pakem metodologi, kemudian hasilnya dipublikasikan kemasyarakat. Disinilah persoalan utama yang menjadi PR lembaga-lembaga survei.
Sudah menjadi rahasia umum, seiring dengan makin percayanya masyarakat terhadap prediksi hasil survei politik, muncul seabreg nama lembaga survei politik baru. Saat ini jumlahnya puluhan. Ada yang hadir karena memang benar-benar ingin memotret dan menunjukkan realitas politik kepada masyarakat dengan metodologi yang semestinya. Akan tetapi tak sedikit yang menyembul hanya ingin mempengaruhi opini massa melalui teori bandwagon effect atau underdog effect. Disinilah yang berbahaya. Jika alasan pendiriannya demikian, maka pakem metodologi akan diterabas dan hasilnya diolah sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga survei bersangkutan.
Berdasarkan kondisi di atas, maka tak mengherankan apabila muncul wacana sertifikasi lembaga survei. Tujuannya baik, untuk membedakan mana lembaga survei yang kredibel dan mana lembaga survei yang abal-abal. Namun siapa yang akan memberikan sertifikat? Apakah pemerintah, organisasi profesi atau siapa?
Sertifikasi memang penting selama lembaga yang akan memberikan sertifikat adalah lembaga yang benar-benar kredibel. Namun, jika yang memberi sertifikat adalah pemerintah, saya ragu. Proses intervensi akan tinggi. Bisa juga, sertifikat dijadikan alat kontrol kepada lembaga survei dengan tujuan politis. Sama halnya dengan SIUPP untuk menerbitkan surat kabar pada zaman Orba. Atau sertifikat diberikan oleh organisasi profesi? seperti AROPI misalnya. Hal ini juga tak menyelesaikan persoalan. Karena tak semua lembaga survei menjadi anggota organisasi profesi tersebut.
Akan lebih baik apabila proses muncul dan matinya lembaga survei ini diserahkan kepada masyarakat. Jika satu lembaga survei memang kredibel, maka dengan sendirinya ia akan tetap eksis. Dan bagi lembaga survei abal-abal, masyarakat saat ini sudah sangat pintar menganalisa. Biarkan vonis masyarakat yang menentukan. Namun yang tak kalah penting adalah peran media massa. Harus ada semacam punishment terhadap lembaga survei yang ”bermain nakal” apabila telah terkait dengan urusan publik. Media massa mempunyai tanggung jawab juga atas apa yang dipublikasikan kemasyarakat dengan mengutip data dari lembaga survei. Oleh karena itu, media harus selektif dalam menurunkan data hasil survei. Jika data lembaga survei tertentu kerap menyimpang dengan hasil faktual, tak semestinya datanya menjadi referensi. Akan tetapi jika data sebuah lembaga survei terbuktif akurat, sudah sewajarnya media menjadikan data lembaga itu sebagai rujukan. Dengan begitu, lembaga survei akan terseleksi dengan sendirinya. Yang pasti, demokrasi kita saat ini sangat membutuhkan instrumen survei politik guna memotret keadaan sosial-kemasyarakat teranyar.