Oleh : Abdul Hakim MS
Koran Sindo, 02 Februari 2006
Setelah menunggu sekian lama, pertanyaan publik tentang siapa yang akan diajukan presiden untuk menjadi panglima TNI, akhirnya terjawab. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyodorkan nama Marsekal (Udara) Djoko Suyanto kepada DPR untuk menggantikan Jenderal Edriartono Sutarto. Dan, ini pun mengakhiri sekian banyak spekulasi tentang siapa yang akan mengisi jabatan tertinggi di tentara ini.
Namun, masalah timbul ketika Djoko Suyanto harus menjalani feat and proper test di DPR. Sebagian kalangan merisaukan hal ini karena rentan nuansa politis. Oleh karena itu perlu untuk ditinjau kembali. Namun pendapat di pihak lain, persetujuan DPR mutlak dibutuhkan agar TNI tidak disalahgunakan menjadi alat penguasa seperti di zaman Orde Baru.
Seperti diketahui, ide bahwa jabatan panglima TNI tidak harus melalui persetujuan DPR, meluncur dari panglma TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Dua hari kemudian, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono pun mengeluarkan gagasan yang sama. Alasannya, panglima TNI merupakan jabatan profesional, bukan jabatan politik. Ketika harus melalui persetujuan DPR, tarik ulur kepentingan politik tidak akan bisa dihindarkan.
Spontan, gagasan ini mendapat kritik dari kalangan anggota DPR. Lukman Hakim Saifudin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Jawa Tengah VI), menghawatirkan bahwa gagasan yang muncul ini akan menggiring institusi TNI kembali menjadi alat kekuasan seperti zaman Orba. Oleh karenanya, uji kelayakan dari DPR, masih harus dilakukan untuk melakukan kontrol terhadap kinerja lembaga yang sah secara UU dalam menggunakan senjata ini.
Pro dan kontra dari kedua pendapat ini, sah-sah saja dalam bingkai negara demokrasi. Politisasi jabatan panglima TNI, adalah bagian proses dari transparansi dalam mengambil sebuah kebijakan. Apalagi, TNI tidak hanya berhubungan dengan presiden, melainkan juga dengan Menteri Pertahanan, DPR, dan Dewan Pertahanan Nasional.
Namun ada hal yang menggelitik. Kebanyakan, yang menentang dihilangkannya ‘kewajiban’ calon panglima TNI untuk ‘sowan’ ke DPR, datang dari kalangan partai politik. Yang menjadi pertanyaan, mengapa jabatan panglima TNI ini sangat diinginkan oleh partai politik?
Hak Pilih dalam Pemilu
Jika ditelisik dari sisi manapun, Djoko Suyanto adalah orang yang layak untuk diberikan giliran menjadi panglima TNI. Selama ini, kedudukan panglima TNI selalu diisi oleh angkatan darat. Namun angkatan laut juga pernah merasakan jabatan ini ketika Abdurrahman Wahid memberikan kepercayaan kepada Laksamana (laut) Widodo AS.
Lalu kenapa PDI-P masih ngotot untuk mencalonkan Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk menjadi calon panglima TNI? Ini tidak lain dilatarbelakangi oleh strategisnya posisi panglima TNI untuk kepentingan komoditas pada pemilu 2009 nanti.
Sebagai pihak yang kemungkinan maju dalam pemilu 2009 nanti, megawati pasti sudah memperhitungkan secara matang tentang besarnya jumlah pemilih di kalangan TNI. Apalagi ditambah dengan organisasi-organisasi dibawah TNI --baik secara langsung maupun yang tidak-- akan menjanjikan dulangan suara yang cukup meyakinkan.
Memang, pada pemilu 2004 lalu, TNI kehilangan hak istimewanya. Mereka harus rela menanggalkan keinginan untuk menyampaikan aspirasi politiknya melalui pemilu. Bahkan, mereka juga harus rela tersingkir dari jatah kursi parlemen sebagai implikasi derasnya tuntutan agar TNI back to barrac dan menjadi tentara yang profesional.
Namun akan berbeda menjelang pemilu 2009 nanti. Hak memilih TNI dalam pemilu akan kembali ada. Hal ini mengacu pada pasal 145 UU no. 12/2003 yang menyebutkan bahwa pada pemilu 2004, anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan hak pilihnya. Artinya, pada pemilu 2009 nanti, besar kemungkinan anggota TNI dan anggota Polri sudah bisa menggunakan hak pilihnya lagi.
Meskipun TNI dan Polri masih banyak mendapatkan pembatasan peran politik, namun posisi strategis TNI dan Polri pada pemilu 2009 ini, mengundang partai politik untuk bisa menuai berkah darinya. Partai politik akan berusaha maksimal agar dapat “menempatkan orangnya” menjadi panglima TNI. Karena dengan begitu, TNI bisa dimobilisasi untuk mengumpulkan suara melalui sistem komando yang kuat.
Contoh kasus betapa TNI dan Polri sangat berpengaruh dalam pengumpulan suara, terjadi pada pemilu 2004 lalu. Seorang anggota Polri bisa mempengaruhi pemilih dilingkungan keluarga besar Polri yang menggunakan hak pilih, baik anak, mertua, istri, veteran dan lainnya. Bahkan, mobil TNI pernah terlibat dalam mobilisasi pengumpulan suara di pesantren Az Zaitun.
Memotong ”Meja politik” Panglima TNI
Jabatan Panglima TNI memang sangat rentan untuk bisa diselewengkan. Kasus mobilisasi pengumpulan suara di Pondok pesantren Az Zaitun pada pemilu 2004 lalu, adalah salah satunya. Oleh karena itu, masihkan proses pengangkatan Panglima TNI ini harus melalui DPR yang rentan dengan kepentingan partai politik?
Ada dua persoalan ketika jabatan Panglima TNI ini masih melalui DPR. Pertama, apabila Panglima TNI dalam pengangkatannya harus melalui parlemen, mau tidak mau, proses politisasi partai politik akan ikut mewarnai. Hal ini dikarenakan posisi TNI yang sangat strategis dalam pemilu atau dalam persoalan lainnya. Padahal, ini tidak lazim karena Panglima TNI adalah jabatan teknis-operasional untuk mengembangkan perencanaan, strategi, dan doktrin operasi militer gabungan, bukan jabatan publik yang mempunyai pertanggungjawaban politik.
Kedua, apabila pengangkatan Panglima TNI masih melalui proses politik DPR, dapat melahirkan politisasi jabatan Panglima TNI. Hal ini sangat rentan karena dapat mengakibatkan dilema jabatan. Bisa saja, Panglima TNI merasa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada seorang Menteri pertahanan. Karena Menteri pertahanan dalam proses pengangkatanya tidak melalui DPR. Keadaan ini bisa menyulitkan hubungan institusional Dephan dan Mabes TNI. Otoritas politik Dephan sedikit luntur atas institusi militer.
Selain dua persoalan diatas, masih banyak yang menjadi rentetatan masalah lain ketika seorang Panglima TNI masih harus melalui ”meja politik” DPR. Utang budi politik kepada parpol, pasti akan terjadi. Oleh karena itu, UU No. 34 tahun 2004 tentang pengngkatan Panglima TNI perlu untuk diamandemen. Harus ditegaskan, bahwa dalam pemilihan Panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden. TNI hanya memegang pertanggungjawaban operasional, bukan pertanggungjawaban politik yang sudah menjadi bagian Menteri pertahanan.
Dengan begitu, seorang Panglima TNI bisa melaksankan tugasnya secara profesional. Semangat yang sudah dibangun dengan mengsampingkan dunia politik, selalu dapat dijaga. Karena seperti orang inggris bilang ”tidak ada makan siang gratis”. Pun dalam dunia politik, ”tidak ada yang gratis bagi partai politik untuk mendorong seseorang menduduki jabatan tertentu”.
Koran Sindo, 02 Februari 2006
Setelah menunggu sekian lama, pertanyaan publik tentang siapa yang akan diajukan presiden untuk menjadi panglima TNI, akhirnya terjawab. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyodorkan nama Marsekal (Udara) Djoko Suyanto kepada DPR untuk menggantikan Jenderal Edriartono Sutarto. Dan, ini pun mengakhiri sekian banyak spekulasi tentang siapa yang akan mengisi jabatan tertinggi di tentara ini.
Namun, masalah timbul ketika Djoko Suyanto harus menjalani feat and proper test di DPR. Sebagian kalangan merisaukan hal ini karena rentan nuansa politis. Oleh karena itu perlu untuk ditinjau kembali. Namun pendapat di pihak lain, persetujuan DPR mutlak dibutuhkan agar TNI tidak disalahgunakan menjadi alat penguasa seperti di zaman Orde Baru.
Seperti diketahui, ide bahwa jabatan panglima TNI tidak harus melalui persetujuan DPR, meluncur dari panglma TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Dua hari kemudian, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono pun mengeluarkan gagasan yang sama. Alasannya, panglima TNI merupakan jabatan profesional, bukan jabatan politik. Ketika harus melalui persetujuan DPR, tarik ulur kepentingan politik tidak akan bisa dihindarkan.
Spontan, gagasan ini mendapat kritik dari kalangan anggota DPR. Lukman Hakim Saifudin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Jawa Tengah VI), menghawatirkan bahwa gagasan yang muncul ini akan menggiring institusi TNI kembali menjadi alat kekuasan seperti zaman Orba. Oleh karenanya, uji kelayakan dari DPR, masih harus dilakukan untuk melakukan kontrol terhadap kinerja lembaga yang sah secara UU dalam menggunakan senjata ini.
Pro dan kontra dari kedua pendapat ini, sah-sah saja dalam bingkai negara demokrasi. Politisasi jabatan panglima TNI, adalah bagian proses dari transparansi dalam mengambil sebuah kebijakan. Apalagi, TNI tidak hanya berhubungan dengan presiden, melainkan juga dengan Menteri Pertahanan, DPR, dan Dewan Pertahanan Nasional.
Namun ada hal yang menggelitik. Kebanyakan, yang menentang dihilangkannya ‘kewajiban’ calon panglima TNI untuk ‘sowan’ ke DPR, datang dari kalangan partai politik. Yang menjadi pertanyaan, mengapa jabatan panglima TNI ini sangat diinginkan oleh partai politik?
Hak Pilih dalam Pemilu
Jika ditelisik dari sisi manapun, Djoko Suyanto adalah orang yang layak untuk diberikan giliran menjadi panglima TNI. Selama ini, kedudukan panglima TNI selalu diisi oleh angkatan darat. Namun angkatan laut juga pernah merasakan jabatan ini ketika Abdurrahman Wahid memberikan kepercayaan kepada Laksamana (laut) Widodo AS.
Lalu kenapa PDI-P masih ngotot untuk mencalonkan Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk menjadi calon panglima TNI? Ini tidak lain dilatarbelakangi oleh strategisnya posisi panglima TNI untuk kepentingan komoditas pada pemilu 2009 nanti.
Sebagai pihak yang kemungkinan maju dalam pemilu 2009 nanti, megawati pasti sudah memperhitungkan secara matang tentang besarnya jumlah pemilih di kalangan TNI. Apalagi ditambah dengan organisasi-organisasi dibawah TNI --baik secara langsung maupun yang tidak-- akan menjanjikan dulangan suara yang cukup meyakinkan.
Memang, pada pemilu 2004 lalu, TNI kehilangan hak istimewanya. Mereka harus rela menanggalkan keinginan untuk menyampaikan aspirasi politiknya melalui pemilu. Bahkan, mereka juga harus rela tersingkir dari jatah kursi parlemen sebagai implikasi derasnya tuntutan agar TNI back to barrac dan menjadi tentara yang profesional.
Namun akan berbeda menjelang pemilu 2009 nanti. Hak memilih TNI dalam pemilu akan kembali ada. Hal ini mengacu pada pasal 145 UU no. 12/2003 yang menyebutkan bahwa pada pemilu 2004, anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan hak pilihnya. Artinya, pada pemilu 2009 nanti, besar kemungkinan anggota TNI dan anggota Polri sudah bisa menggunakan hak pilihnya lagi.
Meskipun TNI dan Polri masih banyak mendapatkan pembatasan peran politik, namun posisi strategis TNI dan Polri pada pemilu 2009 ini, mengundang partai politik untuk bisa menuai berkah darinya. Partai politik akan berusaha maksimal agar dapat “menempatkan orangnya” menjadi panglima TNI. Karena dengan begitu, TNI bisa dimobilisasi untuk mengumpulkan suara melalui sistem komando yang kuat.
Contoh kasus betapa TNI dan Polri sangat berpengaruh dalam pengumpulan suara, terjadi pada pemilu 2004 lalu. Seorang anggota Polri bisa mempengaruhi pemilih dilingkungan keluarga besar Polri yang menggunakan hak pilih, baik anak, mertua, istri, veteran dan lainnya. Bahkan, mobil TNI pernah terlibat dalam mobilisasi pengumpulan suara di pesantren Az Zaitun.
Memotong ”Meja politik” Panglima TNI
Jabatan Panglima TNI memang sangat rentan untuk bisa diselewengkan. Kasus mobilisasi pengumpulan suara di Pondok pesantren Az Zaitun pada pemilu 2004 lalu, adalah salah satunya. Oleh karena itu, masihkan proses pengangkatan Panglima TNI ini harus melalui DPR yang rentan dengan kepentingan partai politik?
Ada dua persoalan ketika jabatan Panglima TNI ini masih melalui DPR. Pertama, apabila Panglima TNI dalam pengangkatannya harus melalui parlemen, mau tidak mau, proses politisasi partai politik akan ikut mewarnai. Hal ini dikarenakan posisi TNI yang sangat strategis dalam pemilu atau dalam persoalan lainnya. Padahal, ini tidak lazim karena Panglima TNI adalah jabatan teknis-operasional untuk mengembangkan perencanaan, strategi, dan doktrin operasi militer gabungan, bukan jabatan publik yang mempunyai pertanggungjawaban politik.
Kedua, apabila pengangkatan Panglima TNI masih melalui proses politik DPR, dapat melahirkan politisasi jabatan Panglima TNI. Hal ini sangat rentan karena dapat mengakibatkan dilema jabatan. Bisa saja, Panglima TNI merasa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada seorang Menteri pertahanan. Karena Menteri pertahanan dalam proses pengangkatanya tidak melalui DPR. Keadaan ini bisa menyulitkan hubungan institusional Dephan dan Mabes TNI. Otoritas politik Dephan sedikit luntur atas institusi militer.
Selain dua persoalan diatas, masih banyak yang menjadi rentetatan masalah lain ketika seorang Panglima TNI masih harus melalui ”meja politik” DPR. Utang budi politik kepada parpol, pasti akan terjadi. Oleh karena itu, UU No. 34 tahun 2004 tentang pengngkatan Panglima TNI perlu untuk diamandemen. Harus ditegaskan, bahwa dalam pemilihan Panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden. TNI hanya memegang pertanggungjawaban operasional, bukan pertanggungjawaban politik yang sudah menjadi bagian Menteri pertahanan.
Dengan begitu, seorang Panglima TNI bisa melaksankan tugasnya secara profesional. Semangat yang sudah dibangun dengan mengsampingkan dunia politik, selalu dapat dijaga. Karena seperti orang inggris bilang ”tidak ada makan siang gratis”. Pun dalam dunia politik, ”tidak ada yang gratis bagi partai politik untuk mendorong seseorang menduduki jabatan tertentu”.







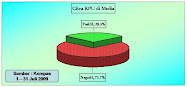
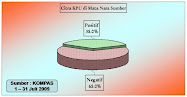
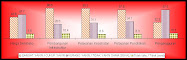


No comments:
Post a Comment