Oleh : Abdul Hakim MS.
Cukup menarik apabila kita meninjau sejarah kepemiluan kita, khususnya meninjau masalah sistem pemilihan umum yang pernah dipakai. Ibarat bayi yang sedang belajar berjalan, begitulah upaya kita mencari format sistem pemilu yang sesuai. Kadang terjatuh, kemudian bangun lagi, dan terjatuh lagi. Tanpa henti, upaya “coba-coba” itu terus dilakukan. Bahkan hingga kini, proses trial and error masih berada dalam area abu-abu (grey area). Belum nampak jelas terlihat sistem pemilu seperti apa yang dapat mengantarkan Indonesia bisa mendayung demokrasi secara sempurna.
Pada Pemilu 1955, kita pernah memakai sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka (open list system). Para pemilih, secara teoritis diberi kesempatan untuk memilih tanda gambar, atau orang yang ada dalam daftar calon dari orsospol peserta pemilu dan perorangan. Tetapi dalam praktiknya, hal itu tidak dilaksanakan oleh orsospol peserta pemilu, sehingga sistem itu hanya berlaku untuk calon perseorangan saja.
Pada pemilu-pemilu Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997), kita memakai sistem proporsional (suara berimbang) dengan kombinasi sistem stelsel daftar mengikat (Closed list system). Para pemilih hanya diberi kesempatan untuk memilih tanda gambar partai saja tanpa mengetahui siapa calon-calon yang akan mereka pilih. Sistem ini pun masih berlanjut hingga era reformasi, yakni pada pemilu 1999. Pemilih tetap “hanya” diberi kesempatan untuk memilih tanda gambar partai, tanpa mengetahui calon-calon yang mereka pilih.
Pada Pemilu 2004, angin segar sempat berhembus terkait sistem proporsional dengan kombinasi sistem stelsel daftar ini. Banyak kalangan yang mengiginkan perubahan terkait dengan sistem stelsel daftar –dari closed list system menjadi open list system. Partai-partai politik pun akhirnya sepakat untuk menggunakan sistem ini dalam percaturan Pemilu 2004.
Akan tetapi sayang, dalam pelaksanaannya, ternyata open list system yang dipakai pada pemilu kedua era reformasi ini banyak mengalami reduksi dari arti esensialnya. Sistem ini tidak diterapkan secara sempurna sehingga banyak mengalami pembiasan. Tidak heran apabila kemudian banyak pengamat menyebutnya sebagai sistem proporsional dengan kombinasi sistem stelsel daftar terbuka “setengah hati”. Atau mungkin bisa saya katakan dengan lebih ektrim, sistem pemilu kala itu merupakan sistem “manipulasi demokrasi”.
Saya sebut dengan “sistem manipulasi demokrasi” karena open list system yang dipergunakan ini sudah jauh melenceng dari arti hakiki yang terkandung didalamnya. Seharusnya, jika memang sistem daftar calon terbuka ini dilakukan dengan murni, maka tidak ada lagi “penutup” yang membuat open list system kehilangan jati dirinya.
Saya melihat, setidaknya ada tiga katup yang menutup kembali open list system pada pemilu 2004 lalu, sehingga menjadikannya lebih mirip closed list system. Pertama, open list ini ditutup kembali dari dimensi tatacara pencalonan anggota legislatif yang memakai nomor urut sebagai cerminan dari ranking. Partai politik berhak mengajukan calon dan menempatkan calon tersebut pada nomor urut keberapa. Bagi calon yang berada pada nomor urut pertama, besar kemungkinan dirinya bisa melenggang ke Senayan. Dengan model seperti ini, maka kekuatan partai politik menjadi sangat dominan. Calon legislatif pun akan lebih loyal kepada partai politik yang mencalonkannya ketimbang kepada basis konstituennya.
Kedua, sistem ini ditutup kembali dari tatacara proses pemberian suara. Pemilih, suaranya akan dianggap sah apabila mencoblos tanda gambar saja, atau mencoblos tanda gambar dan calon. Akan tetapi, suara pemilih dianggap tidak sah apabila hanya mencoblos calon saja. Padahal, calon yang dipilih juga berasal dari partai yang bersangkutan. Tentu, proses seperti ini “melanggar” asas open list system. Seharusnya, apabila pemilih mencoblos tanda gambar sah, mencoblos gambar dan calon sah, maka mencoblos calon saja juga seharusnya sah. Karena calon bersangkutan, pastilah datang dari parpol bersangkutan, bukan dari parpol lain.
Ketiga, sistem ini ditutup kembali pada tatacara penetapan calon terpilih. Seperti kita tahu, patokan untuk memperoleh kursi, calon-calon harus memenuhi batas angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP). Akan tetapi jika tidak ada yang mencapai BPP, dan partai yang bersangkutan mendapatkan jatah kursi disebuah dapil, maka calon yang akan mewakili partai bersangkutan adalah kandidat yang berada pada nomor urut 1. Tentu, kondisi ini juga “melanggar” asas open list system. Seharusnya, jika sistem ini diterapkan secara konsisten, partai yang mendapatkan kursi, akan diserahkan pada calon yang memperoleh suara paling besar, berapapun jumlah perolehan suaranya.
Saat pembahasan paket UU Politik yang sedang berjalan saat ini, persoalan-persoalan di atas harus mendapatkan perhatian serius. Dalam UU Pemilu yang baru, katup-katup penghalang penerapan open list system ini harus dieliminasi. Karena jika tidak, pemilu yang diharapkan menjadi ajang demokratisasi, hanya akan menjadi ajang pesta rakyat tanpa arti.
Niat baik untuk menghilangkan berbagai macam penyumbat ini memang sudah mulai berdatangan. Salah satu keinginan itu datang langsung dari Presiden SBY dengan menggulirkan wacana tentang sistem proporsional dengan kombinasi stelsel daftar terbuka “tanpa nomor urut”. Keinginan kuat pemerintah tercermin dalam draf yang diajukan ke DPR. Dalam draf usulan pemerintah itu, sistem nomor urut yang mencerminkan ranking, akan diganti dengan nomor urut berdasarkan abjad. Selain itu, angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) sebagai prasyarat seorang calon dapat melenggang ke Senayan, juga dieliminasi.
Sudah barang tentu, keberanian pemerintah ini adalah sebuah langkah maju untuk mendukung bergulirnya demokrasi secara benar. Akan tetapi, apakah konsep ini akan mendapatkan persetujuan dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Disinilah letak persoalannya.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa terjadinya pembiasan open list system pada pemilu 2004 lalu, tidak lebih disebabkan oleh “akal-akalan” para elit partai yang “ketakutan” tidak dapat lagi berkantor di Senayan. Kurang dekatnya para wakil rakyat yang ada sekarang dengan para konstituen merekalah yang mengakibatkan munculnya berbagai upaya “penjegalan” penerapan open list system secara konsekwen.
Meski begitu, kita hanya patut berharap agar para wakil rakyat ini dapat membuka mata terhadap gejala kemajuan demokrasi kita. Sudah saatnya mereka menujukkan komitmen terhadap masyarakat, bukan lagi melulu kepada partai politik. Dari cara seperti inilah citra DPR yang selama ini “terbenam” dapat dikembalikan. Dengan tidak menyetujui konsep open list system dijalankan secara konsisten, itu artinya mereka telah menghambat laju demokrasi yang sudah berjalan di atas relnya. Sudah barang tentu, hal ini akan menambah panjang daftar “keculasan” wakil rakyat untuk “memanipulasi demokrasi”.
Cukup menarik apabila kita meninjau sejarah kepemiluan kita, khususnya meninjau masalah sistem pemilihan umum yang pernah dipakai. Ibarat bayi yang sedang belajar berjalan, begitulah upaya kita mencari format sistem pemilu yang sesuai. Kadang terjatuh, kemudian bangun lagi, dan terjatuh lagi. Tanpa henti, upaya “coba-coba” itu terus dilakukan. Bahkan hingga kini, proses trial and error masih berada dalam area abu-abu (grey area). Belum nampak jelas terlihat sistem pemilu seperti apa yang dapat mengantarkan Indonesia bisa mendayung demokrasi secara sempurna.
Pada Pemilu 1955, kita pernah memakai sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka (open list system). Para pemilih, secara teoritis diberi kesempatan untuk memilih tanda gambar, atau orang yang ada dalam daftar calon dari orsospol peserta pemilu dan perorangan. Tetapi dalam praktiknya, hal itu tidak dilaksanakan oleh orsospol peserta pemilu, sehingga sistem itu hanya berlaku untuk calon perseorangan saja.
Pada pemilu-pemilu Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997), kita memakai sistem proporsional (suara berimbang) dengan kombinasi sistem stelsel daftar mengikat (Closed list system). Para pemilih hanya diberi kesempatan untuk memilih tanda gambar partai saja tanpa mengetahui siapa calon-calon yang akan mereka pilih. Sistem ini pun masih berlanjut hingga era reformasi, yakni pada pemilu 1999. Pemilih tetap “hanya” diberi kesempatan untuk memilih tanda gambar partai, tanpa mengetahui calon-calon yang mereka pilih.
Pada Pemilu 2004, angin segar sempat berhembus terkait sistem proporsional dengan kombinasi sistem stelsel daftar ini. Banyak kalangan yang mengiginkan perubahan terkait dengan sistem stelsel daftar –dari closed list system menjadi open list system. Partai-partai politik pun akhirnya sepakat untuk menggunakan sistem ini dalam percaturan Pemilu 2004.
Akan tetapi sayang, dalam pelaksanaannya, ternyata open list system yang dipakai pada pemilu kedua era reformasi ini banyak mengalami reduksi dari arti esensialnya. Sistem ini tidak diterapkan secara sempurna sehingga banyak mengalami pembiasan. Tidak heran apabila kemudian banyak pengamat menyebutnya sebagai sistem proporsional dengan kombinasi sistem stelsel daftar terbuka “setengah hati”. Atau mungkin bisa saya katakan dengan lebih ektrim, sistem pemilu kala itu merupakan sistem “manipulasi demokrasi”.
Saya sebut dengan “sistem manipulasi demokrasi” karena open list system yang dipergunakan ini sudah jauh melenceng dari arti hakiki yang terkandung didalamnya. Seharusnya, jika memang sistem daftar calon terbuka ini dilakukan dengan murni, maka tidak ada lagi “penutup” yang membuat open list system kehilangan jati dirinya.
Saya melihat, setidaknya ada tiga katup yang menutup kembali open list system pada pemilu 2004 lalu, sehingga menjadikannya lebih mirip closed list system. Pertama, open list ini ditutup kembali dari dimensi tatacara pencalonan anggota legislatif yang memakai nomor urut sebagai cerminan dari ranking. Partai politik berhak mengajukan calon dan menempatkan calon tersebut pada nomor urut keberapa. Bagi calon yang berada pada nomor urut pertama, besar kemungkinan dirinya bisa melenggang ke Senayan. Dengan model seperti ini, maka kekuatan partai politik menjadi sangat dominan. Calon legislatif pun akan lebih loyal kepada partai politik yang mencalonkannya ketimbang kepada basis konstituennya.
Kedua, sistem ini ditutup kembali dari tatacara proses pemberian suara. Pemilih, suaranya akan dianggap sah apabila mencoblos tanda gambar saja, atau mencoblos tanda gambar dan calon. Akan tetapi, suara pemilih dianggap tidak sah apabila hanya mencoblos calon saja. Padahal, calon yang dipilih juga berasal dari partai yang bersangkutan. Tentu, proses seperti ini “melanggar” asas open list system. Seharusnya, apabila pemilih mencoblos tanda gambar sah, mencoblos gambar dan calon sah, maka mencoblos calon saja juga seharusnya sah. Karena calon bersangkutan, pastilah datang dari parpol bersangkutan, bukan dari parpol lain.
Ketiga, sistem ini ditutup kembali pada tatacara penetapan calon terpilih. Seperti kita tahu, patokan untuk memperoleh kursi, calon-calon harus memenuhi batas angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP). Akan tetapi jika tidak ada yang mencapai BPP, dan partai yang bersangkutan mendapatkan jatah kursi disebuah dapil, maka calon yang akan mewakili partai bersangkutan adalah kandidat yang berada pada nomor urut 1. Tentu, kondisi ini juga “melanggar” asas open list system. Seharusnya, jika sistem ini diterapkan secara konsisten, partai yang mendapatkan kursi, akan diserahkan pada calon yang memperoleh suara paling besar, berapapun jumlah perolehan suaranya.
Saat pembahasan paket UU Politik yang sedang berjalan saat ini, persoalan-persoalan di atas harus mendapatkan perhatian serius. Dalam UU Pemilu yang baru, katup-katup penghalang penerapan open list system ini harus dieliminasi. Karena jika tidak, pemilu yang diharapkan menjadi ajang demokratisasi, hanya akan menjadi ajang pesta rakyat tanpa arti.
Niat baik untuk menghilangkan berbagai macam penyumbat ini memang sudah mulai berdatangan. Salah satu keinginan itu datang langsung dari Presiden SBY dengan menggulirkan wacana tentang sistem proporsional dengan kombinasi stelsel daftar terbuka “tanpa nomor urut”. Keinginan kuat pemerintah tercermin dalam draf yang diajukan ke DPR. Dalam draf usulan pemerintah itu, sistem nomor urut yang mencerminkan ranking, akan diganti dengan nomor urut berdasarkan abjad. Selain itu, angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) sebagai prasyarat seorang calon dapat melenggang ke Senayan, juga dieliminasi.
Sudah barang tentu, keberanian pemerintah ini adalah sebuah langkah maju untuk mendukung bergulirnya demokrasi secara benar. Akan tetapi, apakah konsep ini akan mendapatkan persetujuan dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Disinilah letak persoalannya.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa terjadinya pembiasan open list system pada pemilu 2004 lalu, tidak lebih disebabkan oleh “akal-akalan” para elit partai yang “ketakutan” tidak dapat lagi berkantor di Senayan. Kurang dekatnya para wakil rakyat yang ada sekarang dengan para konstituen merekalah yang mengakibatkan munculnya berbagai upaya “penjegalan” penerapan open list system secara konsekwen.
Meski begitu, kita hanya patut berharap agar para wakil rakyat ini dapat membuka mata terhadap gejala kemajuan demokrasi kita. Sudah saatnya mereka menujukkan komitmen terhadap masyarakat, bukan lagi melulu kepada partai politik. Dari cara seperti inilah citra DPR yang selama ini “terbenam” dapat dikembalikan. Dengan tidak menyetujui konsep open list system dijalankan secara konsisten, itu artinya mereka telah menghambat laju demokrasi yang sudah berjalan di atas relnya. Sudah barang tentu, hal ini akan menambah panjang daftar “keculasan” wakil rakyat untuk “memanipulasi demokrasi”.







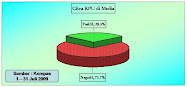
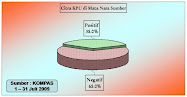
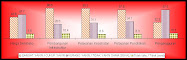


2 comments:
apa kah ada sistem yang sempurna dimata semua pihak?
ga faham..
Hmm.. nanya dong pendapatnya..
Jadi sebaiknya kita sekarang ini pake sistem apa ya? distrik apa proporsional?
Thanks in advance
Post a Comment