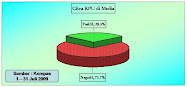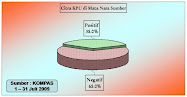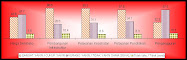Oleh : Abdul Hakim MS
Di era demokrasi langsung seperti yang dianut Indonesia saat ini, topik primordialisme akan selalu hangat diperbincangkan menjelang pemilihan presiden. Maklum, mitos bahwa pemimpin Indonesia harus berasal dari etnis jawa masih cukup kuat disebagian besar kalangan masyarakat kita.
Kita tentu masih ingat dengan ramalan joyoboyo yang mengatakan bahwa pemimpin Indonesia nantinya adalah mereka yang memiliki inisial ‘notonegoro’. Inisial ini memang identik dengan nama-nama dari suku Jawa. Untuk inisial ‘no’ dan ‘to’ telah menjadi kenyataan, yakni munculnya presiden pertama dan kedua, Soekar’no’ dan Soehar’to’. Akan tetapi, untuk presiden ketiga dan seterusnya, ramalan Joyoboyo ini meleset.
Presiden ketiga Indonesia adalah BJ Habibie. Ia tak memiliki inisial yang tersangkut-paut dengan ramalan di atas. Kemudian menyusul presiden berikutnya adalah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiganya juga tak memiliki tautan dengan inisial ramalan tersebut. Merujuk hal ini, muncul pertanyaan yang cukup menarik, yakni masih relevankah menggunakan variabel primordialisme sebagai indikator utama untuk mengkalkulasi peluang keterpilihan seorang presiden saat ini?
Memudar
Ketika masa awal-awal republik ini berdiri, hubungan antara primordialisme dengan keterpilihan seseorang dalam jabatan politik memang cukup kental. Setidaknya, itu yang ditemukan oleh seorang antropolog asal Amerika yang fokus mengkaji Indonesia, Clifford Geertz (1973). Menurut hasil penelitian tokoh yang mempopulerkan istilah priyayi, abangan, dan santri ini, pada awal-awal kemerdekaan, masalah etnik menjadi problematik serius. Tak jarang, adanya persaingan politik antar elit yang memliki perbedaan asal suku kerap berujung pada konflik. Kala itu, Geertz menuding bahwa kompetisi politik antar elit yang berbeda suku inilah yang menjadi faktor utama munculnya konflik antar etnik.
Dalam konteks pemilihan presiden, hasil studi Geertz empat puluh tahun yang lalu ini, hingga sekarang masih menjadi rujukan tunggal terkait hubungan primordialisme dengan keterpilihan tokoh politik. Minimnya literatur yang tak memperbarui temuan Geertz, membuat banyak elit kita yang masih meyakini bahwa primordialisme tetap menjadi variabel dominan dalam menentukan keterpilihan seorang presiden.
Padahal, pasca reformasi bergulir, isu primordial sebetulnya sudah tak lagi menjadi variabel utama dalam menentukan keterpilihan seorang presiden. Keterpilihan SBY pada pemilu 2004 dan 2009, misalnya, lebih dipengaruhi oleh kecemerlangan prestasi lulusan terbaik Akabri angkatan 1973 ini. Selain itu, faktor dinamika politik yang menempatkan SBY sebagai “pihak teraniaya” oleh penguasa, juga menjadi unsur dominan keterpilihannya.
Menjelang pemilu 2014, faktor primordial malah sepertinya akan menjadi variabel terakhir dalam menentukan keterpilihan tokoh politik. Merujuk temuan hasil survei nasional Skala Survei Indonesia (SSI) pada Oktober 2011, mayoritas publik Indonesia ternyata sudah tak mempersoalkan asal suku kala menentukan pilihan presidennya. Saat ditanya dalam menentukan kriteria calon presiden/wakil presiden apakah harus dari keturunan jawa atau keturunan luar jawa, hanya 22.8% yang masih menganut sentimen kesukuan (primordial). Sementara 73.3% menjawab tak penting pemimpin berasal dari suku mana. Bagi masyarakat, yang paling penting adalah pemimpin yang konkrit berbuat untuk rakyat.
Meski masih membutuhkan penelitian lebih dalam, setidaknya temuan SSI dalam survei nasional tersebut bisa ditafsirkan sebagai telah pudarnya sikap primordialisme masyarakat dalam menentukan calon pemimpinnya. Membincangkan asal suku dalam menentukan kriteria pemimpin bangsa sudah tak begitu relevan. Sehingga ke depan, calon pemimpin tak harus terbebani oleh asal suku yang memang sudah given dari Tuhan. Yang paling penting adalah membuat program konkrit bagi kesejahteraan rakyat.
Peluang non-Jawa
Lunturnya sikap primordialisme ini tentu menjadi kabar baik bagi calon presiden yang memiliki asal suku selain Jawa. Seperti banyak diprediksi oleh lembaga survei nasional, selain nama Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, nama yang memiliki elektabilitas baik di mata publik adalah Jusuf Kalla (JK), Aburizal Bakrie (Ical), dan Hatta Rajasa. Ketiganya merupakan tokoh bersuku non-jawa. JK berdarah Bugis, Makassar, Aburizal Bakrie bersuku Lampung, dan Hatta Rajasa berasal dari Sumatera Selatan. Pertanyaannya, bagaimana kans nama-nama dari luar jawa ini untuk bisa memenangi pemilu 2014?
Jika merujuk hasil survei, tiga nama yang telah disebutkan di atas memiliki kans memenangi pemilu yang sama besar. Merujuk hasil survei nasional Skala Survei Indonesia (SSI) pada Oktober 2011, perbedaan tingkat elektabilitas ketiganya masih berada pada area margin of error. Elektabilitas JK ada di angka sembilan persen-an, Ical di angka enam persen-an, dan Hatta Rajasa di angka mendekati enam persen-an. Dengan selisih angka elektabilitas seperti itu, sementara pemilu masih dua tahun lagi, ketiganya masih bisa saling mengalahkan karena waktu sosialisasi masih cukup lama.
Untuk menjadi kandidat capres, ketiganya juga sepertinya tak memiliki kendala serius. JK yang memiliki tingkat elektabilitas baik sepertinya tak akan memiliki kesulitan mencari kendaraan politik untuk pencapresannya. Sedangkan Ical tinggal menunggu waktu untuk dicalonkan Partai Golkar. Sementara Hatta Rajasa telah digadang-gadang Partai Amanat Nasional (PAN) untuk melaju pada pilpres 2014.
Meski demikian, ada beberapa kendala yang bisa mengurangi tingkat kempetitif ketiganya melawan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. JK memiliki kelemahan tak memiliki partai politik serta usianya yang sudah uzur (72 tahun pada pemilu 2014). Sedangkan Ical memiliki catatan buram terkait masih terkatung-katungnya masalah lumpur lapindo dan skandal tunggakan pajak yang dilakukan kelompok usaha Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Sementara Hatta Rajasa diusung oleh PAN yang suaranya terus stagnan di angka 6 – 7 persen saja, selain riak-riak kecil kasus hibah KRL Jepang.
Diluar kekurangannya, capres non-jawa masih memiliki peluang tinggi untuk bisa memimpin Indonesia di masa datang. Lunturnya sikap primordialisme di sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia, menjadikan pintu keterpilihan semakin terbuka. Dan mungkin saja, hal itu akan bisa terjadi pada pemilu 2014 yang dua tahun lagi akan dihelat di negeri ini.
Yang diperlukan oleh calon pemimpin non-jawa saat ini adalah membuat program yang betul-betul bisa menyasar ke hati pemilih. Dengan begitu, kompetisi pada pemilu 2014 nanti akan semakin sengit, sehat, dan beragam seberagam etnik dan kultur yang dipunyai Indonesia.
Baca Selengkapnya...