Seputar Indonesia, 15 Juli 2010
Oleh: Abdul Hakim MS
 Menyimak sambutan Presiden SBY pada pembukaan Konferensi Ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia di Istana Negara pada 13 Juli 2010 cukup menarik dicermati. Presiden berharap, UU pemilu bisa ajeg dan tidak berubah-ubah setiap kali pemilu berlangsung. Hal itu bertujuan agar masyarakat mudah faham dan tidak dibuat bingung. Selain itu, dengan konsitennya UU Pemilu akan bermuara pada terjadinya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
Menyimak sambutan Presiden SBY pada pembukaan Konferensi Ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia di Istana Negara pada 13 Juli 2010 cukup menarik dicermati. Presiden berharap, UU pemilu bisa ajeg dan tidak berubah-ubah setiap kali pemilu berlangsung. Hal itu bertujuan agar masyarakat mudah faham dan tidak dibuat bingung. Selain itu, dengan konsitennya UU Pemilu akan bermuara pada terjadinya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.Pesan presiden di atas memunculkan pertanyaan penting, dapatkah hal tersebut terwujud pada pemilu-pemilu mendatang, khususnya pada pemilu 2014? Ataukah pesan presiden itu hanya akan menjadi paradoks?
Dialektik Terbalik
Salah satu isu penting dalam pembahasan RUU Pemilu adalah upaya dalam penyederhanaan partai politik. Upaya ini dimaksudkan guna menopang sistem presidensial yang kuat. Namun pada faktanya, usaha dalam pengaturan penyederhanaan partai politik dalam UU Pemilu selalu jungkir-balik. Pada pemilu 1999 dan 2004, electoral Trheshol (ET) dipakai untuk maksud tersebut. Akan tetapi belum tercapai tujuan yang diharapkan, ketentuan ini rusak dengan pergantian sistem menjadi Parliamentary Threshold (PT) pada pemilu 2009. Aturan ET pun gugur. Akibatnya, partai politik yang tidak lolos ET pada pemilu 2004, tetap bisa ikut berkompetisi asal mempunyai kursi di DPR. Celakanya, partai yang tidak lolos ET dan juga tidak mempunyai kursi di DPR, akhirnya pun dapat ikut pemilu 2009 berdasarkan judicial reviewe yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
Jungkir-balik aturan ini kemudian membiaskan tujuan awal, penyederhanaan partai politik. Pada pemilu 1999, partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai. Pada pemilu 2004, jumlah partai politik peserta pemilu sebetulnya telah dapat sedikit disederhanakan menjadi 24 partai politik. Akan tetapi, pada pemilu 2009 dengan dilakukan pergantian dari aturan ET menjadi PT, jumlah partai politik peserta pemilu kembali membengkak menjadi 38 partai politik plus 6 partai lokal di Aceh. Bagaiamana dengan pemilu 2014? Apakah PT akan berubah lagi sehingga partai politik yang akan ikut pemilu 2014 tidak hanya 9 partai politik yang lolos PT karena aturan ini dalam UU Pemilu kembali akan mengalami perubahan?
Upaya penyederhanaan ini, jika dikaitkan dengan konsep hegel tentang proses dialektika, menjadi dialektika terbalik. Seperti dikatakan Hegel, proses dialektika dimaksudkan untuk menelurkan antithesis dari thesis yang sebelumnya ada. Dari pertentangan keduanya akan memunculkan sintesis baru. Namun yang perlu dicatat bahwa dalam proses dialektik yang dimaksud Hegel adalah proses pertentangan Thesis dan Antithesis untuk mencari kebenaran mutlak. Oleh karena itu, proses pertentangan keduanya akan menimbulkan sesuatu yang lebih baik dan terus bergerak menjadi lebih baik sampai pada akhirnya berlabuh pada titik kesempurnaan. Namun yang terjadi pada pola penyederhanaan partai politik justeru sebaliknya. Artinya, proses perdebatan dalam penyusunan UU Pemilu tidak kunjung bermuara pada pelaksanaan pemilu dengan jumlah partai politik yang lebih baik. Perdebatan panjang dan alot tentang isu penyederhanaan partai politik pun menjadi sia-sia.
Power-seeking Politician
Pertanyaan kemudian muncul, kenapa dapat terjadi dialektika terbalik? Untuk menjawab pertanyaan ini, penjelasannya dapat ditemukan dalam literatur kajian ekopol neo-klasik. Untuk membedah persoalan-persoalan seperti pembahasan UU Pemilu, misalnya, unit analisisnya dapat difokuskan pada perilaku dua aktor utama, yakni society actor dan state actor. Untuk mengkaji state actor, ada dua fokus utama, yakni telaah terhadap birokrasi dan politisi. Kajian terhadap birokrasi melahirkan model analisis rent-seeking bureucrat. Semetara untuk kajian terhadap politisi, memunculkan model analisis power-seeking politician.
Argumentasi dasar power-seeking politician ini adalah para politisi merupakan makhluk rasional yang tidak steril dari perhitungan untung-rugi dalam setiap mengambil keputusan. Kepentingan utama dari politisi adalah memaksimalkan, dan bila mungkin, mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Untuk tujuan ini, maka para politisi akan dimotivasi oleh keinginan menggunakan sumber daya (resources) apa saja yang dimiliki guna memberikan ganjaran kepada siapa saja yang mendukung mereka, dan memberikan hukuman kepada siapa saja yang mencoba mengganggu (Grindle, 1989).
Implikasi dari argumentasi Grindle di atas, politisi cenderung berfikir kepentingan jangka pendek. Tidak penting bagi para politisi keputusannya nanti akan berdampak seperti apa kepada orang lain. Pertimbangan utamanya adalah; keputusan itu tidak merugikan diri mereka sendiri!
Melihat model ini, maka kita menjadi mafhum kenapa dialektika terbalik seperti uraian diatas bisa terjadi, yaitu karena penentu utama terbentuknya UU Pemilu teretak pada tangan para politisi yang duduk di Senayan. Padahal, mengacu pada penjelasan Grindle, apa yang dilakukan politisi di Senayan bukan mencari sistem yang ajeg dan dapat berlaku dalam jangka yang panjang, melainkan “mengakali” UU Pemilu yang akan dibentuk agar dapat memberi laba pada diri dan institusinya dalam jangka pendek. Dampak dari pola dasar pemikiran seperti ini adalah adanya praktik-praktik kesepakatan di bawah meja atau “politik dagang sapi”. Para politisi tak risau jikalau UU Pemilu akan berganti setiap menjelang pemilu, bahkan mungkin lebih ekstrim, UU Pemilu boleh berganti setiap kali Pilkada, asal dapat memberi keuntungan dan dapat mempertahankan kekuasaan dalam jangka pendek.
Melihat fakta ini, sepertinya kita akan tetap mengelus dada melihat pembahasan RUU Pemilu 2014. Kita menjadi sangsi, pembahasan yang dilakukan dapat menyembulkan UU Pemilu yang benar-benar mapan. Penjara Power-seeking politician lebih kuat dibandingkan harapan akan terciptanya sistem pemilu yang dapat mendukung proses demokrasi dalam waktu yang panjang. Pesan Presiden SBY agar UU Pemilu tidak berubah-ubah akan sulit terwujud dan sepertinya hanya akan menjadi sebuah paradoks.







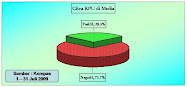
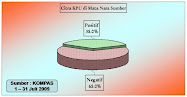
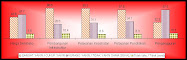


1 comment:
dialam yg demokratis dan serba terang ini masih ada juga yang seharusnya jadi contoh....kok tidak ngasih contoh....
Post a Comment