Oleh : Abdul Hakim MS
Quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dan media massa terhadap hasil Pilkada DKI Jakarta 11 Juli 2012 lalu menyembulkan kontrovesi. Meski masih harus menunggu pengumuman resmi dari KPU, hasil quick count menyiratkan bahwa pasangan Jokowi-Ahok unggul dalam kontestasi menuju DKI-1.
Hal itu terlihat dari hasil quick count Litbang Kompas, misalnya, yang menempatkan pasangan Jokowi-Ahok pada posisi pertama dengan menggamit suara sebesar 42.59%, disusul pasangan Foke-Nara di urutan kedua dengan perolehan suara sebesar 34.32%. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei lain juga menunjukkan perolehan suara yang tak jauh berbeda dengan Litbang Kompas.
Hal itu terlihat dari hasil quick count Litbang Kompas, misalnya, yang menempatkan pasangan Jokowi-Ahok pada posisi pertama dengan menggamit suara sebesar 42.59%, disusul pasangan Foke-Nara di urutan kedua dengan perolehan suara sebesar 34.32%. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei lain juga menunjukkan perolehan suara yang tak jauh berbeda dengan Litbang Kompas.
Syahdan, hasil ini menuai polemik. Bukan pada hasil hitung cepatnya, melainkan kenyataan bahwa pasangan incumbent Foke-Nara dikalahkan oleh pasangan Jokowi-Ahok. Padahal, seminggu sebelum hari pemungutan suara, berbagai lembaga survei mengeluarkan prediksi bahwa pasangan Foke-Nara akan memenangi kontestasi. Bahkan, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang juga menjadi konsultan pasangan Foke-Nara, dengan sangat yakin memproyeksi bahwa pasangan yang ia nasehati itu bisa saja memenangi pilkada dengan satu putaran saja.
Kenyataan di atas menyebabkan banyak kalangan menggugat lembaga penyelenggara survei opini publik. Tak akuratnya prediksi yang dilakukan, menyembulkan pertanyaan tentang metodologi yang digunakan. Pun demikian halnya dengan etika pollster yang mempublikasikan hasil risetnya, padahal ia merupakan konsultan politik kandidat yang ikut berkompetisi.
Namun di luar itu, ada pertanyaan yang cukup menggelitik, yakni apa yang terjadi sehingga pasangan Foke-Nara yang dijagokan banyak lembaga survei bisa kalah dalam Pilkada DKI Jakarta?
Underdog Effect
Melihat fenomena yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta ini, saya jadi teringat dengan fenomena yang sama saat pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1936. Pada pemilu itu, petahana Franklin Delano Roosevelt berusaha mempertahankan kekuasaanya dalam pemilihan presiden melawan Gubernur Kansas, Alfred M. Landon. Yang paling terkenal dan menjadi perdebatan sengit dalam kampanye keduanya kala itu adalah kebijakan New Deal Roosevelt.
Sebelum pemilihan, The Literary Digest, sebuah majalah yang cukup terkenal dan selalu berhasil memprediksi kemenangan pemilihan presiden AS sejak 1916, mengeluarkan hasil survei. Majalah mingguan yang didirikan oleh Isaac Kauffman ini memprediksi bahwa Landon sepertinya akan memangi kontestasi dengan selisih 57 : 43 persen. Akan tetapi, saat pemilu berlangsung, prediksi Digest meleset jauh. Roosevelt ternyata memenangi pemilu dengan raihan 62 persen suara.
Dalam analisis Pierce (1940), kemenangan Roosevelt tak lain disebabkan oleh munculnya underdog effect survei politik. Meski diprediksi kalah, Roosevelt tetap berusaha untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang kandidat yang tangguh, tak dapat ditaklukkan, dan bermental pemenang. Sikap inilah yang kemudian menimbulkan simpati, sentimen positif, dan dukungan yang besar dari masyarakat. Itulah yang disebut Pierce sebagai Underdog Effect dari survei politik.
Apa yang terjadi pada Pilkada DKI beberapa lalu, meski dalam konteks yang berbeda, memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada pemilu Amerika serikat tersebut. Sebelum pemilihan berlangsung, semua lembaga survei menempatkan pasangan Foke-Nara sebagai pasangan yang sepertinya akan bisa dengan mudah memenangi kontestasi. Berbekal hasil riset, yang salah satunya dilakukan oleh konsultannya sendiri, pasangan Foke-Nara kemudian dengan “pongah” mengkampanyekan pilkada cukup dengan satu putaran saja. Padahal, untuk bisa menang dalam satu putaran, pasangan ini mesti harus menggamit suara 50 persen + 1. Dengan jumlah pasangan calon yang berjumlah enam pasang, untuk mendapatkan suara 50 persen tentu bukanlah perkara mudah.
“Kepongahan” incumbent ini, hemat penulis, membuat pemilih Jakarta jengah. Hal itu dikarenakan incumbent dalam lima tahun ini dipandang nyaris tak berbuat apapun untuk mengurai masalah keseharian yang dihadapi warga Jakarta. Macet masih menjadi pemandangan umum setiap hari, pun demikian dengan banjir di beberapa wilayah yang tak juga teratasi. Tak mengherankan apabila kemudian tingkat kepuasan warga jakarta terhadap kepemimpinan Foke dalam lima tahun ini masih di bawah 50 persen.
Dalam situasi seperti ini, pemilih jakarta kemudian mendapati sosok alternatif pemimpin yang “terbukti” mampu memimpin daerah asalnya. Jokowi yang merupakan Wali Kota Solo, merupakan kepala daerah yang dipandang cukup berhasil oleh masyarakatnya. Setidaknya keberhasilan Jokowi tercermin dari survei terhadap warga Solo yang menempatkan tingkat kepuasan masyarakat di atas 90 persen.
Ditambah publikasi reputasi yang cukup baik, seperti gebrakan mobil Esemka dan gaya kepemimpinan yang luwes, membaur, dan dekat dengan masyarakat, sosok Jokowi seolah bisa memberikan harapan baru bagi perubahan di Jakarta. Hal ini sangat kontras dengan gaya kepemimpinan Foke yang terkesan elitis dan eksklusif. Bagi pemilih Jakarta, apa yang tidak ditemui dalam diri Foke ada di dalam sosok Jokowi.
Dari titik inilah kemudian muncul rasa simpati, sentimen positif, dan dukungan yang besar dari masyarakat Jakarta. Kesan tidak “pongah” di tengah “kepongahan” incumbent, membuat posisi Jokowi bisa menuai underdog effect survei politik seperti yang di tuai oleh Roosevelt pada pemilu Amerika Serikat tahun 1936. Dari sosok yang tidak diunggulkan menjadi sosok yang sangat disanjung dan disayang.
Gagalnya Bandwagon Effect
Dalam konteks yang lain, munculnya underdog effect menjadikan harapan terjadinya bandwagon effect terhadap publikasi hasil survei pilkada DKI Jakarta tak terpenuhi. Bandwagon effect adalah dampak yang diinginkan agar pemilih yang belum punya pilihan bisa mengikuti suara mayoritas. Seperti kita tahu, survei LSI (lingkaran) seminggu sebelum pemilihan masih menempatkan pasangan Foke-Nara pada tingkat elektabilitas 49,1 persen. Sementara pasangan Jokowi-Ahok berada di angka 14,4 persen.
Melihat elektabilitas Foke-Nara yang sudah di atas angin tersebut, maka hasil survei ini pun di publikasi dengan massif. Dengan hanya kekurangan 1 persen suara saja untuk bisa memenangi pilkada satu putaran, pasangan incumbent kemudian dengan yakin memasang jargon pilkada satu putaran ke seluruh pelosok Jakarta. Namun naas, harapan terjadinya badnwagon effect malah berbalik menjadi underdog effect untuk pasangan Jokowi-Ahok.
Pesan yang bisa ditarik dari situasi ini adalah, secara etis, idealnya lembaga pembaca aspirasi publik ketika merilis hasil surveinya tidak memiliki kepentingan langsung dengan kandidat yang sedang berkompetisi. Karena jika hal itu dilakukan, kecurigaan bahwa hasil riset yang dipublikasikan hanya digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini masyarakat ke arah yang diharapkan (bandwagon effect) tidak bisa dihindari. Akibatnya, akan banyak gugatan terhadap survei politik seperti saat ini.








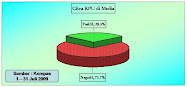
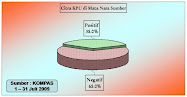
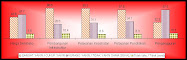


2 comments:
tdk hanya partai politik yang jualan mas, lembaga survei pun ikut2an JUALAN
Mantap!! Kalau parpol and lembaga surveinya ada Ɣªήğ doyan jualan. Ayo dorong bersama "Pembeli " Ɣªήğ cerdas.
Post a Comment