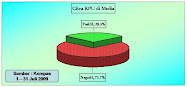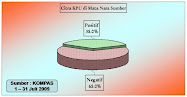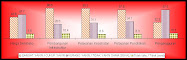Suara Pembaruan, 13 Desember 2006
Ada gejala menggembirakan bila menatap wajah demokrasi Indonesia tujuh tahun ke belakang. Penyelenggaraan Pemilu 1999 dan 2004, di tengah segala kekurangannya, banyak mendapatkan pujian. Dua pemilu terakhir, dipandang sebagai titik tolak tegaknya demokrasi di bumi pertiwi, karena pintu kebebasan sudah mulai dibuka dan kemandirian berekspresi begitu dihargai.
Namun ironis. Di tengah demokrasi yang sudah mulai mapan ini, ada kecenderungan yang kurang sinergis. Sejak Pemilu 1971 hingga ke Pemilu 2004, tren persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya terus melorot. Bahkan yang lebih parah, titik penurunan itu terjadi saat demokrasi dan kebebasan sangat terbuka lebar di negeri ini, yakni Pemilu 1999 dan 2004.
Pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput, naik menjadi 7,2 persen dibandingkan Pemilu 1997 yang hanya 6,4 persen saja. Lebih ironis lagi, penurunan partisipasi itu terjadi saat Pemilu 2004 lalu.
Dalam tiga rangakaian pemilu yang diselenggarakan secara berurutan kala itu, sebanyak 16 persen dari pemilih terdaftar tidak menyumbangkan suaranya untuk pemilu legislatif. Kemudian, angka ini mengalami kenaikan menjadi 21,77 persen pada saat pilpres putaran pertama.
Pada akhirnya, angka ini kembali mengalami kenaikan pada saat pilpres putaran kedua menjadi 23,37 persen. Padahal, dalam Pemilu 2004, sistem pemilu sudah berubah menjadi pemilihan secara langsung dan euforia demokrasi sedang marak-maraknya.
Yang menjadi pertanyaan, kenapa kepercayaan masyarakat terhadap pemilu menjadi rendah?
Kita memang patut miris jika melihat tingkat partisipasi masyarakat yang terus menyusut dari pemilu ke pemilu. Namun, yang dilakukan masyarakat itu, tentu bukan tanpa alasan. Ada latar belakang yang menjadikan mereka kemudian lebih memilih untuk tidak memilih dalam pemilu.
Saya melihat, setidak-tidaknya, ada tiga alasan utama kenapa kepercayaan masyarakat begitu rendah terhadap lembaga pemilu. Pertama, karena publik sudah merasa tidak pernah terwakili oleh partai politik yang dijagokannya.
Harapan besar yang sempat menggenang di dada para pemilik suara ketika memasuki bilik pencoblosan, melayang begitu saja kala aspirasi mereka hanya dipandang sebelah mata oleh partainya.
Publik yang merasa dizalimi oleh partai politik ini, terekam dalam survei LSI yang dipublikasikan pada Maret 2006 yang lalu. Dalam survei itu, lebih dari 50 persen masyarakat menyatakan kecewa dengan kinerja partai politik.
Bahkan, survei yang dilakukan berbarengan dengan isu santer kenaikan BBM dan impor beras kala itu, dibanding lembaga publik lainnya seperti presiden, polisi, tentara, dan DPR, parpol dinilai paling buruk kinerjanya. Hampir semua pemilih tidak tahu sikap dan keputusan partai tentang dua isu penting yaitu kenaikan BBM dan impor beras.
Hubungan psikologis antara masyarakat dan partai politik pun begitu rendah. Dalam survei yang dilakukan oleh LSI di awal 2006, hanya sekitar 25 persen saja dari pemilih yang punya hubungan psikologis secara positif dengan parpol. Selebihnya, pemilih merasa buta dengan kondisi partai politik. Padahal di negara demokrasi seperti AS ataupun negara-negara Eropa Barat, hubungan psikologis antara pemilih dan partai politik rata-rata di atas 60 persen.
Kedua, publik sudah mulai gerah dengan kepongahan para elite politik Tanah Air. Boleh dikatakan, komitmen para elite politik untuk memperbaiki diri, baik dari kinerja, perilaku, maupun keberpihakannya, belum juga terwujud. Manuver dan citra yang mereka munculkan, kebanyakan menerabas keadilan publik.
Ambil sebagai salah satu contoh, tersebarnya video mesum dari kalangan anggota DPR yang banyak dipergunjingkan akhir-akhir ini. Kasus ini adalah cerminan bagaimana perilaku para elite politik memang jauh dari harapan masyarakat. Bisa jadi, kasus yang terungkap ini hanyalah gumpalan gunung es.
Padahal, saat ini masyarakat sedang diresahkan oleh kelangkaan BBM. Mereka harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan 5-10 liter minyak tanah. Di sisi lain, anggota DPR yang merupakan wakil untuk memperjuangkan aspirasi mereka, sedang terbuai membuat film porno dan "berasik-masyuk" bersama selingkuhannya.
Ketiga, publik sudah mulai pandai menganalisa kondisi politik atau sudah beranjak ke pemilih yang rasional. Ini dilatarbelakangi oleh santernya perkembangan teknologi. Hampir setiap keluarga, sudah memiliki media televisi yang menyalurkan informasi padat tentang kondisi politik nasional. Media televisi telah merubah karkter berpikir mereka kala disuguhkan kejadian dan perilaku para elite politik.
Di samping itu, penyebaran penduduk juga akan menjadi salah satu indikator masyarakat akan lebih pandai dalam menentukan sikapnya. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, konsentrasi penduduk akan beralih ke wilayah perkotaan.
Jika selama ini konsentrasi penduduk lebih banyak di daerah pedesaan, empat tahun ke depan proporsi penduduk kota melesat menjadi 54,2 persen dari total 234 juta jiwa penduduk Indonesia. Angka itu cukup signifikan dibandingkan dengan proporsi penduduk kota tahun 2005 yang hanya 48 persen.
Tentu, pergeseran ini akan menguatkan perubahan perilaku politik masyarakat yang terekam selama ini. Banyak pengamat meyakini bahwa perilaku politik di tengah masyarakat pemilih di Indonesia mulai berubah selama satu dekade terakhir, seiring dengan arus kebebasan dan upaya demokratisasi yang makin gencar. Dan, untuk dapat mengakses arus kebebasan dan upaya demokratisasi ini, daerah perkotaan tentulah lebih bisa memenuhinya dibandingkan daerah pedesaan.
Prospek Suram
Jika melihat ketiga faktor di atas, sepertinya kita akan suram menatap prospek partisipasi masyarakat pada Pemilu 2009 mendatang. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, keresahan masyarakat dengan kepongahan para elite politik plus pemilih yang sudah rasional, akan semakin mereduksi partisipasi pada pemilu mendatang.
Terkait dengan pemilih rasional, yang perlu diwaspadai adalah pemilih pemula. Kelompok ini merupakan pemegang jumlah suara terbanyak dalam pemilu. Dan kelompok ini merupakan sasaran empuk untuk dibidik dalam pemilu mendatang. Para pemilih muda yang menjadi potensi besar dalam Pemilu 2009 adalah pemilih pemula dan yang telah mengikuti satu atau dua pemilu sebelumnya, yaitu mereka yang berusia 18 sampai 30-an tahun.
Catatan proyeksi penduduk Indonesia yang dibuat Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 sebesar 231,3 juta jiwa, 70 persen di antaranya adalah kelompok usia pemilih. Kelompok pemilih muda tercatat merupakan jumlah terbanyak di antara kelompok usia pemilih.
Pada Pemilu 2009, dari sekitar 170 juta penduduk, 59 persen di antaranya adalah pemilih yang berusia 20-40 tahun. Inilah kelompok yang paling berpotensi untuk dirangkul. Namun, kelompok ini juga yang rentan menjadi kelompok golongan putih alias golput. Dalam kelompok ini banyak terangkum pemilih dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang lebih kritis daripada kelompok usia lain. Meskipun tidak ada angka pasti, sebagian pengamat yakin sebagian besar golput berasal dari kelompok ini.
Melihat fakta di atas, sudah sewajarnya apabila partai politik dan elite politik harus start mulai dari sekarang untuk membenahi diri. Karena jika tidak, maka apatisme masyarakat terhadap lembaga pemilu akan terus menglami penyusutan. Dampaknya, legitimasi terhadap hasil pemilu juga akan dipertanyakan dan pemilu sebagai landasan nilai demokrasi, tidak akan lagi menjadi cerminan suara masyarakat secara utuh.