Oleh : Abdul Hakim MS
Ketika menerima pimpinan delegasi International Conference Principles for Anti Corruption Agencies (ACA) di Istana Negara pada November 2012 yang lalu, ada pernyataan menarik yang dikeluarkan Presiden SBY terkait usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut presiden, upaya pemberangusan praktik rasuah di tanah air telah menuai hasil nyata. Namun disaat yang bersamaan, Presiden SBY juga masih belum puas atas capaian yang sudah diraih selama ini.
Memang, kalau diamati, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah membuahkan hasil nyata berupa mulai terbangunnya budaya takut korupsi di setiap lini pemerintahan, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun seiring dengan itu, prilaku penggerogotan terhadap uang negara ini juga ternyata makin massif terjadi. Naasnya, korupsi malah menjangkit disemua lini kehidupan bernegara, baik di pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam kaca mata Presiden, korupsi yang mewabah disemua lini ini sebagai konsekwensi atas diberlakukannya sistem desentralisasi kekuasaan (distribution of power) pasca reformasi 1998. Jika dahulu kekuasaan mutlak ada di tangan pemerintah pusat sehingga korupsi hanya beredar di Jakarta saja, kini dengan adanya distribution of power dalam kerangka otonomi daerah, berimplikasi juga terhadap terjadinya distribution of corruption di pemerintahan-pemerintahan daerah.
Adanya distribution of corruption ini bisa kita tengok dari data yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejak tahun 2004 hingga 2012, ada sebanyak 281 kepala daerah yang sudah tersangkut masalah hukum, baik dengan status tersangka, terdakwa, saksi, atau terpidana. Dari jumlah tersebut, 70 persennya merupakan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Merujuk fakta ini, cukup wajar apabila Presiden SBY menjadi gusar. Asa kepada para kepala daerah agar bisa berprilaku baik, tenyata tak sesuai harapan.
Melihat kondisi di atas, ada pertanyaan menggelitik yang harus dijawab, yakni apakah proses distribution of power-nya yang salah sehingga korupsi kini menjangkit disemua lini pemerintahan?
Ketegasan Hukum
Hemat saya, tidak ada yang salah dengan proses distribution of power yang dilaksanakan pasca reformasi 1998. Secara teoritis, jika sebuah Negara tak ingin ada kekuasaan mutlak oleh penguasa, distribution of power merupakan hal yang wajib dilakukan. Pemberlakukan ini bertujuan agar balance of power antar lembaga Negara bisa terwujud sehingga terjadi check and balance untuk saling mengawasi. Karena sebagaimana adagium popular dalam ilmu politik yang dikemukakan Lord Acton, power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (siapa yang memegang kekuasaan, ia memiliki kecenderungan untuk korup. Dan siapa yang memegang kuasaan secara mutlak, maka pasti ia akan korup).
Jika ada beberapa aturan tentang distribution of power yang belum sempurna, misalnya aturan tentang Pilkada, kita tentu masih bisa maklum karena perjalanan usia reformasi baru menginjak angka 14 tahun. Namun membebankan semua kesalahan pada proses suksesi kepemimpinan didaerah secara langsung juga bukanlah sikap yang bijak. Yang harus terus digalakkan untuk memerangi korupsi menurut hemat saya adalah adanya ketegasan proses hukum terhadap para penggaruk uang Negara.
Namun alih-alih tegas, kita boleh miris dengan proses ketegasan hukum kita dalam mengadili terpidana korupsi. Merujuk catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), Sejak dibentuk di daerah pada tahun 2010, pengadilan tipikor yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak perang melawan korupsi, malah telah memvonis bebas 51 terdakwa kasus korupsi. Dari jumlah itu, 25 terdakwa diantaranya disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, 15 terdakwa di Pengadilan Tipikor Samarinda, 4 terdakwa masing-masing di Pengadilan Tipikor Bandung dan Makassar, 2 terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, dan 1 terdakwa di Pengadilan Tipikor Palembang. Data ini belum ditambah dengan kinerja miris lembaga penagak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan.
Melihat kondisi di atas, sangat beralasan apabila kemudian Presiden SBY meradang. Karena seperti diketahui bersama, sejak awal pemeritahannya, Presiden SBY sudah menabuh genderang perang terhadap praktik rasuah. Bahkan menjelang Pilpres 2009, SBY menggunakan pemberantasan korupsi sebagai tema utama kampanyenya.
Minim Dukungan
Sebenarnya, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemerintahan SBY sudah berada pada jalur yang baik. Sejak 2005 misalnya, Presiden SBY tak segan mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap 155 pejabat negara yang terindikasi tersangkut masalah korupsi. Dari jumlah tersebut, 20 diantaranya adalah para gubernur. Namun sayang, komitmen Presiden ini seolah berjalan sendirian. Banyak pihak malah menujukkan sikap sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebenarnya, dukungan DPR sangatlah penting agar Indonesia bisa segera keluar dari jerat akut virus korupsi. DPR sebagai lembaga legislasi, seharusnya bisa membuat aturan sangsi yang menjerahkan para pelakunya. Namun alih-alih mendukung, sikap DPR malah sering menimbulkan pertanyaan banyak kalangan karena kerap bersikap sebaliknya.
Sikap-sikap DPR yang dianggap tidak pro pemberantasan korupsi misalnya upaya pelemahan terhadap kewenangan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) yang memiliki rapor lumayan baik melalui upaya revisi UU Nomor 30 Tahun 2003 tentang KPK. Seandainya tidak mendapat banyak hujatan dari masyarakat, mungkin UU ini sudah diubah dengan menghilangkan kewenangan penuntutan dan penyadapan KPK. Padahal, dari dua kewenangan inilah KPK bisa menyokok para koruptor.
Kita juga tentu masih ingat dengan upaya penolakan komisi III terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dalam rapat-rapat dengar pendapat hingga masa akhir jabatan keduanya. Alasan DPR kala itu, karena Bibit Chandra dianggap masih memiliki masalah hukum, karena status depoonering yang dikeluarkan Kejaksaan Agung tidak lantas menghilangkan status tersangka keduanya.
Kita pun juga tak bisa lupa dengan ide DPR untuk membubarkan KPK. Saat berlangsung rapat konsultasi DPR dengan KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung pada awal Oktober 2011 silam, Fahri Hamzah dari FPKS dengan garang meminta KPK ditiadakan. Alasanya, KPK yang telah menjadi lembaga superbody, dianggap mencederai asas demokrasi. Yang lebih membuat geram banyak pihak adalah upaya menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM guna mencegah pembebasan bersyarat 7 terpidana korupsi kala itu. Bukankah kebijakan tersebut sebagai upaya pemberian efek jera terhadap para koruptor?
Belum lagi sikap kepolisian yang hingga detik ini masih “bersitegang” dengan KPK. Bahkah ketegangan keduanya sempat memunculkan lelucon “cicak vs buaya” hingga dua jilid. Bukankah situasi seperti ini hanya membuat senang para koruptor?
Itu sebabnya, semua elemen masyarakat tak boleh lelah untuk mengawal proses mematikan praktik korupsi di tanah air. Karena hanya dengan pengawasan dari publiklah yang saat ini masih bisa membuat lembaga penegak hukum tak bersikap seenaknya. Pers, lembaga swadaya masyarakat, dan para pegiat anti korupsi lainnya harus menjadi mata yang tajam dan tak tak boleh kalah. Karena jika lelah dan kalah, tentu yang diuntungkan adalah mereka yang memakan uang Negara di tengah tangisan jutaan masyarakat yang didera kemiskinan.








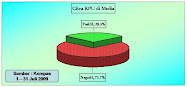
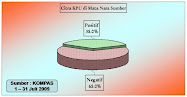
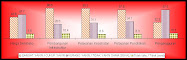


No comments:
Post a Comment